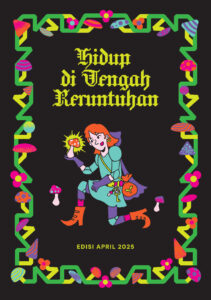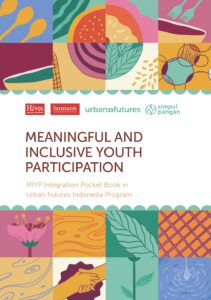Masih ingat apa yang terjadi di Malaysia tanggal 8 Desember lalu? Puluhan ribu orang etnis Melayu berkumpul untuk menuntut pemerintah menolak ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.[1] Sederhananya, mereka mau pemerintah menolak kesetaraan hak etnis-etnis yang ada di malaysia, dan tetap memberlakukan perlakuan istimewa terhadap ras Melayu. Perlakuan istimewa ini termasuk pemberlakuan kuota dalam sektor pendidikan dan pekerjaan. Etnis Melayu akan mendapatkan porsi dan kesempatan lebih besar untuk diterima sekolah atau kerja. Sedangkan etnis Tionghoa dan India hanya mendapatkan kesempatan yang lebih kecil. Sentimen terhadap keturunan Tionghoa muncul juga karena mereka dinilai “pelit” untuk berbagi strategi bisnis. Sama halnya ketika kamu sakit hati ketika temanmu naik jabatan karena kerja kerasnya, sedangkan kamu kerjanya cuma ngemil. Para simpatisan 812 berpendapat bahwa memang seharusnya Malaysia menjadi negara untuk etnis Melayu dan memberlakukan hak istimewa terhadap mereka. Kok, terdengar seperti supremasi kulit putih ya? Dalam hal ini, supremasi etnis Melayu.
Indonesia memiliki sejarah sentimen yang serupa saat pemerintahan Suharto, dan masih tersisa hingga saat ini. Bedanya, sentimen ini diinisiasi oleh seorang presiden. Pada tahun 1967, Suharto menetapkan Instruksi Presiden No. 14 tentang kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Ya, Suharto menyebutnya Cina, menggantinya dari istilah Tiongkok atau Tionghoa yang dinilai memiliki asosiasi psiko-politis dan berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia.[2] Apa coba? Dalam peraturan yang sama Suharto juga “menganjurkan” (baca: memaksa) warga keturunan Tionghoa yang masih menggunakan nama asli Cina menggantinya dengan “nama Indonesia”. Selain itu, keturunan Tionghoa juga tidak bisa merayakan Imlek secara publik layaknya Idul Fitri atau Natal. Perayaan Tahun Baru Cina harus dilakukan di lingkungan keluarga saja, tidak boleh terlihat mencolok. Mungkin saking takutnya Suharto ketularan jadi sipit. Entahlah.
Tulisan ini tidak akan membahas lebih lanjut apa yang terjadi di Malaysia pada Desember 2018, atau membahas lebih panjang apa saja dosa Suharto yang menyengsarakan banyak orang saat dia berkuasa. Tapi, tulisan ini “hanya sekadar mengingatkan”, bahwa peraturan-peraturan yang menimbulkan sentimen terhadap kelompok tertentu, dan diskriminatif terhadap ras, jenis kelamin, kepercayaan, atau identitas tertentu masih banyak di Indonesia. Peraturan-peraturan ini dapat memunculkan ketimpangan yang sangat bertolak belakang dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya terdapat 421 peraturan yang diskriminatif, termasuk di dalamnya peraturan yang melarang perempuan untuk keluar malam dan larangan transpuan bekerja di salon.[3] Mungkin karena saking bejatnya laki-laki di Indonesia sehingga perempuan “dianjurkan” untuk tetap di rumah pada malam hari. Tapi sayangnya, dan anehnya, tidak ada peraturan yang melarang laki-laki untuk mengganggu perempuan.
Slogan “Ganyang Cina”, “Tolak LGBT”, dan “Tolak Ahmadiyah” memang tidak banyak ditemukan dalam keseharian, tapi akan banyak muncul menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Setiap. Saat. Bahkan, ada sekelompok orang yang tidak segan untuk memasang baliho bertuliskan “Haram Pemimpin Non Muslim”. Jika ini muncul dari masyarakat, mungkin masih dapat diredam dengan penertiban atribut jalan yang sudah termasuk sebagai ujaran kebencian. Dengan kata lain, kebodohan masyarakat bisa ditertibkan. Tapi akan jadi masalah ketika kebodohan ini mewabah di pembuat kebijakan atau kepala daerah tertentu. Tidak hanya satu, tapi puluhan atau bahkan ratusan daerah di Indonesia. Katakanlah pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat oleh pemerintah setempat.[4] Pelarangan ini didasarkan oleh kekhawatiran yang tak beralasan karena “meresahkan warga” dan “sesat”. Warga setempat agaknya sangat rapuh karena selalu resah terhadap sesuatu. Apakah mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat sampai-sampai takut keyakinan orang lain akan mempengaruhi keyakinan mereka? Hal yang sama juga terjadi terhadap pelarangan LGBT, apakah mereka takut suatu saat orientasi seksualnya berubah?
Keberadaan kelompok minoritas di tengah-tengah masyarakat yang, katakanlah, homogen nyatanya tidak menimbulkan dampak buruk. Bukankah sesuatu yang dilarang seharusnya adalah hal yang merugikan? Sebut saja larangan mencuri, korupsi, membunuh, begal, menculik, dan kekerasan lainnya. Yang seharusnya diatur dalam peraturan (dan mendapatkan hukuman) adalah tindakan yang merugikan, bukan karena semata-mata identitas orang tersebut. Jika penyebaran HIV selalu dikaitkan dengan LGBT, dan dengan demikian terdapat larangan terhadap LGBT, lantas mengapa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan Islam? Toh, yang menjadi teroris (hampir) selalu orang Islam. Mohon maaf, hanya sekadar mengingatkan.
Bagi kamu yang penasaran, peraturan apa saja yang masih diskriminatif di Indonesia, kamu bisa cek di tautan berikut:
Referensi:
[1] CNN Indonesia. (2018). Usai Reuni 212, Oposisi Malaysia Gelar Aksi Tandingan ‘812’. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181207144105-106-351885/usai-reuni-212-oposisi-malaysia-gelar-aksi-tandingan-812
[2] Raditya, Iswara N. (2018). Intrik Politik Soeharto yang Melarang dan Membelokkan Makna Imlek. Tirto.id. Diakses dari: https://tirto.id/intrik-politik-soeharto-yang-melarang-dan-membelokkan-makna-imlek-cENG
[3] BBC. (2018). Perda-perda yang Diskriminatif menurut Komnas Perempuan. Diakses dari: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46261681
[4] Komnas Perempuan. (2010). Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi. Diakses dari: https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/PP2_Atas%20Nama%20Otonomi%20Daerah.pdf