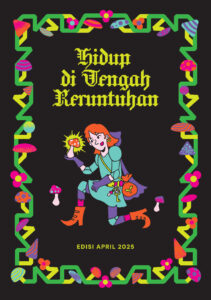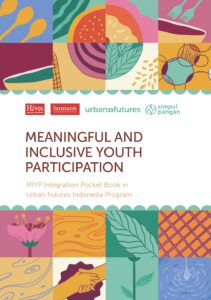Menjadi peduli terhadap kelompok rentan adalah satu hal, namun berbicara atas nama mereka adalah lain soal.
Problem representasi kita kerap kali dihadapkan pada kurangnya keterwakilan ragam identitas gender, seksualitas hingga kejamakan pengalaman dari kelompok masyarakat tertentu. Starting point yang berbeda dan ketiadaan akses yang setara untuk dapat berada di panggung yang sama adalah salah satu sebab yang mengakibatkan problem ini mengada.
Memperbincangkan sesuatu tentu saja diperlukan keahlian dan pengetahuan yang sepadan akan topik yang hendak dibahas. Namun, pendapat ahli saja tak cukup. Pengalaman personal seseorang yang terlibat langsung dengan topik yang sedang dibicarakan juga penting. Perlu ada ruang untuk mendialogkan keduanya secara setara dan inklusif, sehingga perspektif yang berkelindan selama diskusi pun akan kaya dan berimbang.
Bayangkan saja, bila topik yang tengah diangkat adalah “Nanti Kita Cerita tentang Nyeri Menstruasi” tetapi yang diberi ruang menjadi pembicara adalah cis-male semua. Benar memang bahwa semuanya adalah dokter mumpuni dan spesialisasi Obgyn, namun menihilkan pengalaman personal seseorang yang memiliki rahim untuk berbicara mengenai “nyeri menstruasi.”
Tentu saja, bila menggenggam bilah pisau “kebebasan berekspresi” maka siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara. Pada pertarungan wacana di platform yang lebih luas, siapapun dapat turut andil menggumam pendapat dan menyatakan keterlibatan. Namun, bila wacana sosial yang tengah bergulir berkaitan dengan kelompok rentan, apakah formulanya akan tetap sama?
Pada wacana #PapuanLivesMatter yang masih dan tengah kita perjuangkan hingga saat ini misalnya, siapa sebenarnya yang paling berhak untuk berbicara?
Satu kunci penting yang dapat kita jadikan pintu masuk pemahaman adalah topik yang hendak kita respon berkait langsung dengan kelompok rentan. Kelompok masyarakat minoritas yang dimarginalkan dan mengalami kekerasan struktural selama bertahun-tahun. Pelbagai stigma disematkan secara sistematis kepada kawan-kawan Papua. Suara mereka juga telah dibungkam sejak lama. Tercatat ada banyak sekali represi yang terjadi, belum lagi yang tidak tercatat. Tak sedikit pula dari kawan-kawan yang bersuara dan melawan ini taruhannya ialah nyawa.
Berangkat dari adanya latar tersebut, yang pertama bisa kita lakukan adalah cek privilege. Sadari ruang, pengalaman dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian, belajarlah untuk diam dan mendengarkan.
Bukan, bukan berarti kita tidak boleh berbicara mengenai hal yang tengah kita resahkan. Namun, sebelum berbicara tentang kekerasan yang tak pernah kita alami mari belajar lebih dahulu untuk mendengarkan. Mendengarkan teriakan kawan-kawan Papua yang selama ini terbungkam, kemudian bersuaralah dengan cara mengamplifikasi pesan mereka, menyebarluaskannya.
Mengapa kita harus berhati-hati berbicara tentang Papua? Lagi-lagi karena pengalaman personal hingga kolektif yang dihidupi berbeda. Kita tidak mengalami kekerasan sistemik dan rasanya diliyankan sejak lahir. Ya, kita harus speak up mengenai rasisme dan mengajak orang lain untuk aktif menyuarakan ketimpangan ini. Namun, kita tak bisa berbicara atas nama mereka yang terdampak rasisme.
Bagi kita anak muda yang memiliki platform, baik lingkup kecil maupun besar, gunakan pengaruh kita untuk mengamplifikasi suara-suara dari kelompok yang mengalami langsung ketertindasan ini. Tahu diri dan jujur akan kapasitas sendiri. Belajar untuk minggir dan beri privilege panggung yang kita miliki kepada kawan-kawan Papua.
Stop berpikir bahwa kawan-kawan ini adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Sadari bahwa pola pikir yang telah terhegemoni di kepala itu merupakan bibit-bibit dari upaya peminggiran atau eksklusi terhadap mereka.
Kawan-kawan ini sangat paham apa yang mereka butuhkan. Yang perlu kita lakukan adalah belajar mendengar, mengedukasi diri akan kondisi sosial yang terjadi dan mengembalikan ruang kepada mereka yang berhak bersuara.
Hal ini berlaku pula ketika kita hendak menyatakan keberpihakan kepada kelompok rentan yang lain, misalnya kawan-kawan difabel dan LGBTIQ+. Starting point yang tak sepadan, dari mulai diskriminasi yang dialami, ketiadaan bermacam akses yang setara, dan pembungkaman yang nyata pada kawan-kawan yang dianggap “berbeda” ini perlu kita pahami lebih dulu.
Mengatasnamakan diri atas ketertindasan yang tak pernah benar-benar kita alami adalah hal yang jahat sekali. Kita tak ubahnya panitia atau para panelis dokter cis-male dalam diskusi yang berbicara tentang “nyeri menstruasi” tadi.
Menjadi sekutu (allies) pada hal-hal yang dianggap “tabu” oleh konstruksi kaku-normatif masyarakat, membuat kita dipaksa banyak belajar hal yang membahagiakan. Bahwa tak semuanya ialah perihal kedirian; perihal citra; dan konten yang akan ditampilkan. Melainkan perihal kepekaan, bahwa sesekali kita perlu berbagi ruang; pada mereka yang benar-benar ditindas oleh ketidakadilan.
Ada konteks ruang dimana kita semestinya berbicara, ada konteks waktu pula dimana kita sebaiknya diam. Kita telah dilatih untuk berani bersuara. Namun, sepertinya kita juga mesti belajar untuk berani mendengarkan. Berangkat dari konsep pemikir India, Gayatri Spivak, Mari! Pass the mic! Let the Subaltern speak!
Ditulis oleh: Himas Nur
Himas Nur, tercatat sebagai mahasiswa Kajian Budaya dan Media Pascasarjana UGM serta Koordinator Divisi Acara Women’s March Yogyakarta. Kini tengah merawat akun instagram @himasnur.
*) Tulisan ini merefleksikan pandangan pribadi penulis dan berada di luar editorial Pamflet