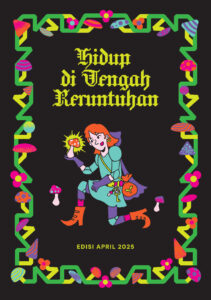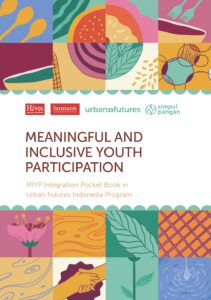Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu merupakan semboyan yang senantiasa kita dengar di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi, apakah semboyan itu kita bawa juga dalam kehidupan sehari-hari?
Latar budaya Indonesia yang sangat beragam membuat istilah toleransi dan diskriminasi bukan lagi istilah yang asing. Pelajaran di sekolah semasa kita SD selalu membuat saya mengasosiasikan kata toleransi dengan perdamaian. Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang selalu tersenyum dan berbicara dengan ramah satu sama lain, meski penampilan, pakaian, warna kulit mereka berbeda-beda. Musik-musik lembut mengalun selalu muncul juga di bayangan saya itu, benar-benar membangun suasana damai. Saya selalu berpikir bahwa toleransi dan diskriminasi seperti air dan minyak yang tidak mungkin bersatu. “Mana mungkin orang yang paham nilai toleransi, mendiskriminasi orang lain yang berbeda darinya, kan? Mana mungkin di dunia indah penuh perdamaian seperti itu ada orang yang mendiskriminasi orang lainnya? Kalau sampai itu terjadi, berarti dunia itu gak toleransi dong?”
Semakin dewasa, saya memahami toleransi dan diskriminasi sebagai suatu kontinum dimana keduanya berada di ujung ekstrim yang berbeda. Hal ini saya pahami setelah melihat banyaknya orang yang merasa dirinya toleran, tetapi hanya pada suatu kelompok atau identitas tertentu yang berbeda darinya. Misalnya, ada orang yang toleran dengan orang lain yang berbeda agama dengannya, tetapi tidak dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda darinya. Atau bisa jadi juga ada orang yang toleran terhadap orang lain dari Suku A, B, C, D tetapi tidak tidak dengan suku E, F, dan G. Apa orang ini bisa dianggap tidak memahami nilai toleransi?
Salah satu pernyataan mind-blowing yang saya baca akhir-akhir ini adalah definisi toleransi yang ditawarkan Walzer (1999). Walzer menjelaskan bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku penerimaan yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang tidak disukainya (resigned acceptance). Ternyata, si nilai toleransi yang kita agung-agungkan dari SD itu bisa hadir dan kita rasakan setelah didahului oleh perasaan tidak suka. Bisa jadi tidak suka terhadap suatu perilaku tertentu, misal guru di kelas yang mentoleransi keterlambatan kita masuk kelas, atau pada identitas orang lain, misal saya mentoleransi orang yang yang jenjang pendidikannya di bawah saya. Intinya, pelaku toleransi adalah orang-orang yang sebenarnya punya kuasa untuk tidak mentoleransi hal yang tidak ia sukai, tapi memutuskan untuk menerima dan tidak melakukan apapun terhadap hal yang tidak ia sukai tersebut (Engelen & Nys, 2008).
Hal ini makin memperjelas pemahaman saya bahwa toleransi dan diskriminasi itu memang berada di suatu kontinum panjang. Keduanya didasari oleh perasaan tidak suka dari kelompok yang punya kuasa. Pembeda keduanya hanya setipis keputusan si pelaku untuk menerima hal yang tidak ia sukai dan tidak berbuat apa-apa, atau menolak hal yang tidak ia sukai dan melakukan sesuatu kepada hal yang tidak ia sukai tersebut. Realisasi ini membuat saya bergidik ngeri. Bayangkan betapa banyaknya kelompok yang tidak punya kuasa menggantungkan hidupnya pada penerimaan atau penolakan kelompok yang lebih memiliki kuasa.
Membongkar pemahaman pribadi saya mengenai kata toleransi yang dulu saya percaya sepenuh hati membuat saya memahami perkataan banyak orang akhir-akhir ini, toleransi saja tidak cukup. Kalau hanya bergantung dengan toleransi, maka kita akan hidup dibawah bayang-bayang kecemasan kapankah si kelompok pemilik kuasa memutuskan untuk tidak toleran, toh rasa tidak sukanya akan ada terus kan?
Banyak yang menawarkan solusi-solusi karena toleransi saja memang tidak cukup. Ada yang mendorong inklusivitas, ada yang menawarkan untuk saling menghargai, menghormati, dan mencintai, dan ada juga yang mendorong rasa saling penerimaan. Walzer (1999) menjelaskan berbagai sikap seseorang atau kelompok ketika berhadapan dengan perbedaan, salah satunya merupakan pluralisme yang melihat perbedaan sebagai sesuatu fakta /realitas sosial yang tidak hanya mewarnai kehidupan, tetapi juga perlu dipertahankan dan dirayakan. Orang-orang dengan paham pluralisme ini akan mendorong adanya perbedaan (enthusiastic endorsement of difference) yang pada akhirnya memberikan wadah bagi siapapun untuk memiliki otonomi diri yang bermakna. Tentunya dengan adanya kondisi ini, setiap individu, terlepas dari identitas dan latar belakangnya, dapat berkembang pada potensi penuhnya.
Beranjak dari toleransi ke pluralisme tentu tidak mudah. Mengamini pluralisme berarti membuang habis rasa tidak suka yang jadi pondasi toleransi dan diskriminasi, dan mulai memaknai perbedaan dengan sikap positif. Jangan lupa, pluralisme juga membentuk kita menjadi manusia yang mau mendorong adanya perbedaan. Bukan sekedar membuka ruang-ruang untuk orang yang berbeda (dan bisa jadi tidak punya kuasa) tetapi juga mendukung mereka untuk dapat mengisi ruang-ruang tersebut.
Referensi:
Engelen, Bart & Nys, Thomas. (2008). Tolerance: A Virtue? Towards a Broad and Descriptive Definition of Tolerance. Philosophy in the Contemporary World. 15. 10.5840/pcw20081515.
Khadafi, M. (25 Desember 2015). Diakses pada 13 September 2020 dari https://kabar24.bisnis.com/read/20151225/15/504869/uskup-agung-jakarta-toleransi-saja-tidak-cukup?fb_comment_id=1006191622755494_1006269989414324
Napitupulu, E. L. (4 Desember 2011). Diakses pada 13 September 2020 dari https://edukasi.kompas.com/read/2011/12/04/15404549/tidak.cukup.toleransi.saja.tetapi.menerima.keragaman
Satuharapan.com. (20 Mei 2016). Diakses pada 13 September 2020 dari http://www.satuharapan.com/read-detail/read/hilmar-farid-toleransi-saja-tidak-cukup
Walzer, M. (1999). On Toleration. London: Yale University Press.