Di hari tertentu dalam bulan September, terdapat sejumlah postingan bertema hitam di kanal sosial media seperti Instagram dan Twitter. Akun seperti KontraS, Amnesty International Indonesia, Aksi Kamisan, dan banyak akun-akun bertema HAM lainnya sama-sama mengunggah post bertagar #SeptemberHitam. September Hitam adalah sebuah sebutan yang dibuat untuk menandakan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia di masa lalu. Dari mulai kasus pembunuhan Munir di tanggal 7 September, tragedi Tanjung Priok 12 September, tragedi Semanggi II 24 September, dan juga genosida 1965.
Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian tersebut seolah semakin terasa jauh. Korban, penyintas, dan keluarga korban yang mengalami peristiwa kekerasan terus menua. Generasi baru juga terancam tidak tahu menahu karena isu pelanggaran HAM masa lalu bukanlah sejarah arus utama.
Namun, ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mau kalah dengan waktu. Dengan cara yang beragam, mereka menggiati pelanggaran HAM masa lalu. Sembari Hari Perdamaian Dunia juga dirayakan di tengah #SeptemberHitam ini, kami ingin berbicara mengenai perdamaian bersamaan dengan pelanggaran HAM masa lalu. Untuk itu, kami mengajak empat teman yang aktif dalam isu HAM masa lalu untuk bercerita mengenai apa yang menghubungkan mereka dengan pelanggaran HAM masa lalu dan makna damai.

Benang Merah yang Tak Bisa Dilepaskan, Kusut, dan Diikat Sendiri
Bagi Banu, seorang pegiat HAM, keterikatannya dengan pelanggaran HAM masa lalu begitu jelas dan tidak bisa dipungkiri. Walaupun ia berkenalan dengan isu HAM melalui kerja-kerja penelitian terkait intoleransi agama dan gender di bangku kuliah, pelanggaran HAM sudah lebih dahulu ia temui melalui ibunya.
Aminatun Najariyah, nama ibu Banu, dituding terlibat dalam Peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. Aminatun lalu dipenjara selama 3 bulan dan hidup dengan trauma berat setelah dibebaskan.
“Aku waktu itu tidak mengerti,” ujar Banu ketika mengingat masa kecilnya. “Keterkaitanku dengan kasus ibuku… sebenarnya aku juga ga tau [bagaimana], selain aku mempertanyakan kenapa aku ditinggal waktu SMP.” Banu bercerita bahwa harus tinggal bertiga saja bersama saudara karena ibu ditemani bapak menjalani proses pengadilan HAM Ad Hoc pada 2004.
“Aku cuma menyadari kalo ibuku suka mimpi buruk. Mimpi buruknya selalu soal tentara. Bahwa tentara mengejar-ngejar dia, sepatu lars tentara menginjak-nginjak dia, tentara mau memperkosa dia,” timpalnya. “Adikku sampe sekarang masih cerita bahwa ibu masih mimpi dan berteriak-teriak gitu.”
Bak hubungannya dengan ibu, terlintas sebuah benang merah yang mengikat Banu dan Peristiwa Tanjung Priok. Benang tersebut kusut dan kerap mengganggu masa kecilnya, sehingga ia pelan-pelan harus menguraikan apa yang sebenarnya dialami ibu dan penyintas lain di luar sana. Mengingat bahwa pelanggaran HAM berat bisa dibuka kembali dalam pengadilan tanpa tenggat waktu, Banu dengan gigih menjadi ‘penerus perjuangan keadilan untuk kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984’.
Walaupun keterkaitan Banu dengan pelanggaran HAM masa lalu hadir dari rumah sendiri, cerita teman-teman lain berbeda. Ada Munti, Vino, dan Irma yang pelan-pelan mengulurkan dan mengikat benang merah antara diri mereka dan isu yang berjarak bagi kebanyakan generasi muda ini.
Munti adalah seorang lulusan S1 Pengembangan Masyarakat Islam UIN Yogyakarta asal Magelang. Sewaktu kuliah semester 4, ia mendaftarkan diri untuk menjadi relawan menemani lansia atau simbah-simbah penyintas pelanggaran HAM berat 65 yang diadakan oleh Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM). Menjadi relawan, ia dan teman-teman lainnya bertugas untuk menemani para lansia setidaknya satu kali dalam dua minggu. Aktivitas yang biasa mereka lakukan adalah menemani keseharian para simbah, mendengarkan cerita mereka, menemani mereka ke fasilitas kesehatan, hingga menemani ke rumah ibadah.
Ketika ditanya tentang apa yang membuat Munti merasa terikat dengan peristiwa 65, ia menjawab bahwa pertemuan dan kedekatan yang terjalin dengan para simbah menjadi alasan yang membuat ia merasa terikat dengan peristiwa 65. Penggalan sejarah yang telah diterima Munti dari cerita pengalaman penyintas seolah memberinya sebuah tanggung jawab untuk berbuat sesuatu. Setidaknya, ia bisa membantu membangun kesadaran di masyarakat sekitar mengenai peristiwa 65 dan diskriminasi yang masih terus dialami korban.
“Aku sudah kenal lama dengan mereka. Awalnya hanya tahu simbah ini adalah korban kekerasan G30S, sama seperti mahasiswa pada umumnya. Setelah semakin banyak tahu, setelah memproses banyak informasi, aku semakin tahu ternyata para simbah memiliki pengalaman yang berbeda dari lansia umumnya…. Yang membuatku lebih terikat, karena aku bersinggungan langsung dengan para simbah sehari-harinya, aku semakin melihat dan paham kebutuhan mereka sebagai lansia.”
Selain itu, Munti juga ingin tetap menggeluti kerelawanannya karena ingin terus membagikan pengetahuan yang telah ia dapatkan kepada para mahasiswa yang baru akan memulai menjadi relawan. Sebagai anak muda, Munti merasakan sebuah dorongan untuk terus melanjutkan kerja FOPPERHAM dengan melihat dan merasakan kegigihan dan semangat dari para penyintas 65 untuk terus bertahan.
“Aku malu dengan mereka, seriously. Mereka sudah bangun jam 5, sudah bekerja, bertahan untuk hidup, tetap berjuang. Aku dalam hidup gak minta kaya, tetapi ya gimana caranya aku tetap bisa hidup dengan sebaik hidup. Jadi lebih sering juga karena aku malu, sebagai anak muda yang secara akses dan fasilitas lebih mudah harusnya aku bisa lebih belajar banyak hal.”
Sama seperti Munti, kedekatan Vino dengan HAM didominasi dengan peristiwa 65.

Vino adalah pegiat komunitas Sanggar Seni di Palu. Sewaktu ada sepupunya yang akrab dengan aktivitas Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulteng, ia dipenuhi dengan keraguan untuk ikut serta karena takut disematkan dengan stigma terkait narasi tunggal G30S versi negara. “Yang menjadi ketakutanku pertama itu karena teman-teman SKP-HAM mengurus korban 65 yang notabenenya itu kalau kita bicara dengan masyarakat pasti dibilang pro dengan PKI,” ujar Vino.
Namun, proses berpikir Vino berubah setelah mengakrabkan diri dengan SKP-HAM. Mengenal pengalaman penyintas 65 yang haknya ditiadakan sangat menggugah Vino. “Banyak cerita yang bahkan sampai ketika kita dengar ceritanya itu sakit kepala karena tidak mampu menampung,” jelasnya. “Muntah-muntah, sakit. Karena ada perlakuan-perlakuan yang [di] masa lalu itu yang terlalu sadis, begitu.”
Cerita-cerita ini seolah menyulap rasa ragu dan takut menjadi semangat untuk membantu penyintas yang selama ini tidak mendapatkan haknya. Keterikatan Vino hadir secara perlahan dan organik, sampai di titik sekarang di mana ia merasa “bisa [menggeluti aktivitas SKP-HAM] di sini sampai mati, karena ya cuma itu yang bisa saya buat untuk orang-orang tua.”
Beranjak ke Aceh, kami berbincang dengan Irma, seorang relawan di Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK). Irma tinggal di Aceh Utara, lebih tepatnya di Kota Lhokseumawe. Sebelumnya Irma berkuliah di Universitas Malikussaleh dan berkenalan dengan penyintas Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh melewati sebuah kegiatan peringatan MoU Helsinki yang dilakukan kelompok mahasiswa bersama dengan RPuK. Dari situ, Irma kemudian bergabung menjadi relawan hingga saat ini. “Nah, disitu ketika aku terlibat dengan penyintas, aku masih mencari-cari hal yang menarik dari sejarah konflik ini apa. Lama-lama, aku mendengar cerita, ternyata hal yang menarik adalah banyak sejarah itu yang sebenarnya disembunyikan.”
Setelah bertemu dengan para penyintas, Irma merasa bahwa identitas dirinya sebagai anak muda tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik yang terjadi di Aceh. “Kalau aku gak mau belajar tentang ini, nanti aku ditipu sama sejarah. Kalau aku gak mau cari tahu tentang kebenaran, kita mencari kebenaran bukan berarti kita memprovokasi pihak tertentu, tapi masa sih aku ditipu sama sejarah negara aku sendiri, sama sejarah daerah aku sendiri,” jelasnya. Bagi Irma, kita harus mencari kebenaran sejarah apabila ingin memiliki masa depan yang damai. Kita juga perlu menyuarakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penyintas, yang kebanyakan adalah lansia. “Kan mereka sudah tua, sudah lansia sebagian, kan tidak mungkin mereka sendiri yang memperjuangkan haknya,” tukasnya.
Irma merasa ia mendapatkan dorongan untuk terus bertahan dari semangat para penyintas dan juga dukungan masyarakat yang ia terima. Ibu-ibu penyintas dampingan RPuK biasanya menunggu-nunggu kapan mereka akan mengadakan acara, bahkan kalau harus merelakan pendapatan harian dari bekerja kutip atau kupas pinang di kebun. Dukungan dari pengurus desa dan kecamatan tempat RPuK melakukan kegiatan juga menambah semangat Irma untuk terus berkegiatan bersama para penyintas.

Mengenai Damai
Setiap bulan September datang, seperti sekarang ini, Banu dipertemukan dengan rutinitas yang familiar: diundang untuk memperingati Peristiwa Tanjung Priok. Ajakan konferensi pers, diskusi, maupun wawancara berdatangan.
Sembari aktivitas-aktivitas ini dilaksanakan dengan kesibukannya di KontraS dalam kerja-kerja pemantauan impunitas sepanjang tahun, ia menjadi paham betul bahwa kebanyakan korban pelanggaran HAM masa lalu merasa sangat lelah dan pesimis. Maka, damai bagi Banu adalah terwujudnya transitional justice, yakni konsep penegakkan keadilan yang menekankan adanya transisi komprehensif terhadap demokrasi dan pemenuhan HAM.
Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, transitional justice idealnya mengharuskan negara untuk membantu korban pelanggaran HAM kembali ke masyarakat dan hidup dengan layak. Ini artinya meletakkan kepentingan korban di setiap langkah yang mencakupi rehabilitasi, kompensasi, dan reparasi bagi korban, penyintas, dan keluarga korban.
Lebih lanjut, keadilan tidak bisa diwujudkan tanpa peniadaan impunitas. “Damai itu ya negara tidak memberikan praktik-praktik impunitas lagi terhadap pelaku,” tutur Banu. “Sehingga korban tidak sakit hati lagi terhadap negara. Ini PR terbesar. Lagian, sebenarnya apa salahnya sih ngga ngasih panggung ke orang yang CV-nya udah ngga bagus?”
Masih dalam nada yang sama, damai yang dibayangkan Vino adalah “tidak adanya lagi korban-korban pelanggaran HAM.” “Tapi,” tambahnya, “itu tidak mungkin toh, selama negara ini masih ada. Bahkan sampai kiamat.” Mengingat peran negara yang berkewajiban melindungi warga sipilnya, pernyataan ini meninggalkan rasa ironi yang begitu pahit.
Vino kemudian melanjutkan bahwa ketidakmungkinan tersebut bisa diisi dengan wujud damai melalui pemulihan. Ia mengaku merasa lebih tenang ketika melihat penyintas setidaknya mempunyai kapasitas mental untuk memproses pengalaman getir masa lalu. Tapi, meminjam pertanyaan Irma mengenai kondisi penyintas, “apakah damai sudah mereka rasakan?”
“Aku bertanya lagi apakah damai sudah mereka rasakan. Kalau mereka belum merasakan damai, aku belum merasakan damai yang sesungguhnya juga.” Walau Irma secara pribadi memaknai damai sebagai kebebasan untuk berekspresi, bersuara, dan menyampaikan pendapat; ia merasa bahwa damai bagi kita tidak akan bisa terwujud apabila penyintas kekerasan masa lalu belum mendapatkan damai sejati. “Kalau mereka belum damai, aku juga belum damai karena aku juga bagian dari para penyintas,” jelasnya sekali lagi.
Bagi Munti, arti damai bagi dirinya sendiri adalah saat kita dapat hidup saling peduli dan saling mengerti orang-orang di sekitar kita. Dari contoh paling sederhana, di tengah pandemi ini kita saling peduli dan menanyakan kabar tetangga kita apakah sudah makan atau tidak. Kepedulian ini muncul tanpa terbatasi perbedaan identitas yang menempel pada kita. Dalam konteks lebih pelanggaran HAM, kepedulian ini juga yang Munti harapkan muncul di antara masyarakat umum dengan para penyintas 65 yang masih terus mendapat stigma dan diskriminasi.
Melihat Masa Lalu Demi Masa Depan

Hubungan yang terjalin dengan pelanggaran HAM masa lalu memberi banyak pelajaran yang sulit didapatkan di tempat lain. Vino belajar mengenai bagaimana ia bisa mengambil peran dalam kondisi-kondisi yang meresahkan kompas moralnya. “Aku belajar tentang hidup dari simbah,” ungkap Munti. Irma belajar bahwa sejarah tidak pernah hanya mempunyai satu sisi dan bahwa ia perlu mencari kebenaran sejarah karena sejarah adalah bagian dari dirinya. Sementara itu, Banu memahami diri sendiri melalui pelanggaran HAM masa lalu dan bahwa ada harapan bagi generasi mendatang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
Adapun sekumpulan obrolan ini meyakinkan kami bahwa pelanggaran HAM masa lalu memang harus dihadapi bersama. Tidak seperti namanya, pelanggaran HAM masa lalu justru memiliki peran penting di masa sekarang dan masa depan. Banu, Munti, Vino, dan Irma menunjukkan bahwa meskipun bukan merupakan generasi pertama penyintas ataupun tidak mengalami secara langsung, damai milik kita semua terusik oleh kekerasan masa lalu.
Setelah kamu membaca tulisan ini dan melihat dunia dari mata pegiat isu ini walau sejenak saja, apakah rasa resah dan kepedulian turut muncul? Jika iya, yang bisa kami tawarkan adalah pengingat berikut: kita bisa bersama-sama mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu demi masa sekarang dan mendatang yang lebih damai. September Hitam bisa perlahan dipulihkan dari kekelamannya.


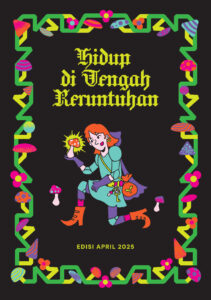

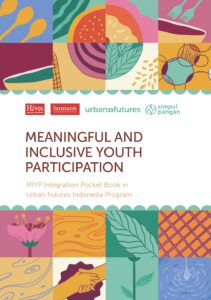
Satu tanggapan untuk “Tentang Damai, Tentang Masa Lalu”
Semoga makin banyak anak muda yg terlibat utk penegakan HAM, berkat Pamflet dan pegiat muda lain! Dorong terus perbaikan buku sejarah, sejarah lokal juga perlu menonjolkan kasus2 setempat.