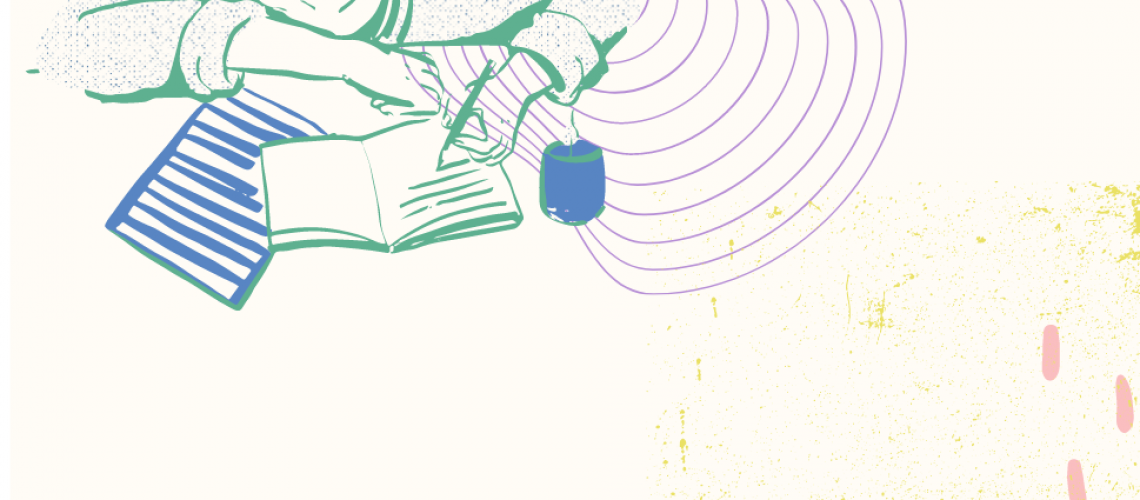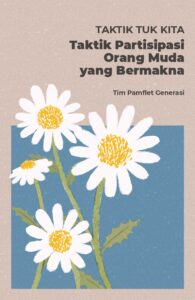Dear pembaca,
Saat ini, menjadi puitis bukanlah solusi. Tetapi, rasanya aku terjerat dalam satu emosi yang itu-itu saja. Sangat melelahkan. Emosi itu lahir tanpa nama. Iya, aku tak tahu namanya… Suatu emosi yang lahir pada bulan Mei.
Emosiku yang ini bagai kotak kecil yang terselip di antara banyak makna emosi lainnya. Ia menyamar–terasa sedih, tapi bukan kesedihan; takut, tapi bukan ketakutan; senang, tapi sesungguhnya bukan itu. Akupun dilanda kebingungan… Bulan Mei adalah bulan membingungkan bagiku…
Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia psikologi manusia, aku pun tahu bahwa koleksi emosi akan semakin kompleks semakin kita dewasa. Aku merasa senang bahwa bulan Mei tahun ini mendapati hari raya lintas agama dan toleransi. Namun, aku masih sedih dengan kondisi pergolakan HAM, pergolakan gender, dan seksualitas.
Walaupun semakin dewasa banyak dari kita yang suka memangkas habis emosi yang tidak perlu demi terlihat dewasa–serta mengutamakan bagian-bagian hidup lainnya–ini berbeda. Aku tidak mau memangkas atau membuat emosi yang belum kukenal menjadi peliharaan yang aku atur semauku. Aku mau mengenalnya terlebih dulu.
Singkatnya, sebagai seorang humanis aku merasa teman-teman lesbian, gay, biseksual, transgender dan lainnya semakin merasa kesulitan untuk tinggal dan menetap di negara ini. Iya, sulit. Akhir-akhir ini banyak sekali phobia terhadap LGBTQ+ yang bertebaran di media sosial. Aku melihat langsung di media sosial, salah satunya, bagaimana sebuah teori ngasal yang berkata bahwa LGBTQ+ menular dan bahwa minoritas gender serta seksualitas adalah penyakit yang harus dimusnahkan. Wujud-wujud phobia ini malah menakuti diriku sendiri dan membuatku bertanya-tanya: Mau sampai kapan Indonesia harus alergi terhadap LGBTQ+? Sampai kapan?
Hal yang anehnya lagi tapi nyata, aku sebagai penulis bukan menjadi bagian dari identitas tersebut. Pembaca boleh berpikir dan menerka aku seperti “mereka” yang akan berkata “harus dong diedukasi, LGBTQ+ bisa memusnahkan populasi manusia, loh”. Nyatanya tidak. Emosiku dan perasaanku tidak berkata demikian. Justru sebaliknya, aku merasa takut. Aku tidak terima adanya diskriminasi dan phobia ini.
Mungkin pembaca bertanya-tanya, kenapa aku memilih menjadi ally bagi teman-teman LGBTQ+? Singkatnya beberapa tahun lalu, aku punya sahabat dekat yang sedang kebingungan terhadap identitas diri. Rasanya hampir setiap pekan kami berkonseling dan aku betul-betul paham apa yang ia rasakan dan ia inginkan. Aku paham bagaimana ia setiap hari bergejolak batin karena mendapat diskriminasi dari banyak pihak.
Sejak menjadi konselor pun, aku tidak suka setiap orang dibanding-bandingkan dan diminta untuk keluar dari kenyamanan dirinya sendiri. Aku tidak suka jika ada orang yang berkata ini hanya masalah kurang iman dan pendirian, justru aku lebih sakit hati melihat temanku tidak bisa menjadi dirinya sendiri.
Aku sempat kehilangan energi dan minat dalam mengerjakan apapun. Aku seperti diajak bermain puzzle di dalam otakku sendiri. Kenapa seekstrem ini kebencian manusia terhadap manusia lain? Bagaimana seharusnya? Apakah aku pantas berbicara mengenai ketidaknyamanan yang kurasakan terkait ini?
Bagian paling sulit mempelajari manusia adalah pada tahap seperti ini. Banyak yang menghakimi, tidak peduli hati nurani. Aku takut masyarakat akan terus menghakimi LGBTQ+.
Iya, seperti itu kurang lebih. Aku tahu aku tidak bisa membungkus perasaanku dalam tulisan ini seutuhnya. Tetapi, bagiku saat ini aku masih mencari nama yang tepat untuk emosiku. Ia bukan emosi yang membingungkan. Ia hanya emosi yang belum menemukan jati dirinya.
Sebagai penutup, aku sekadar ingin berpuisi. Puisi gelap yang hanya bisa dibayangkan di kamar sambil menutup mata:
Suar, berteriak.
Suara dalam ombak
Menggebu layaknya api
Tak padam ditelan sunyi
Klasik, bisikku
Perasa yang sedang sedih
Merasakan itu
Sama, sepertiku.
Jiwa tak pernah salah
Hanya karena kita terlalu membelanya
Membelokkan apa yang disebut dengan “norma”
Padahal,
Ia tempatnya,
Naluri bekerja
Kita memang bukan binatang
Tapi naluri layak untuk ditantang
Teriaklah kawan
Nalurimu berhak untuk sekawan
Berteman dengan akal sehatmu
Yang kau rasakan, valid itu
Marahlah pada emosimu kawan
Jika itu bisa menghilangkan beban
Tak apa melawan
Yang penting pilumu tak lagi terbelenggu
Klasik
Ya, aku tau puisi ini tidak asik
Tidak menarik
Tapi semoga bisa memantik
Emosi yang tak punya nama itu…
***
Selamat Hari Raya IDAHOBIT.
Ditulis oleh: A.I.