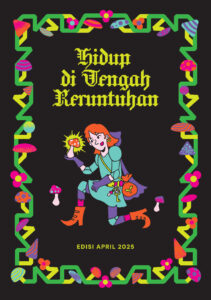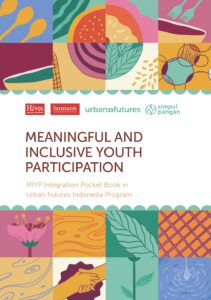Ditulis oleh Mt Fauzan
Ketika Orwell bertugas sebagai polisi imperial yang ditempatkan di Kota Burma, ia melihat kesedihan dan rasa jijik yang amat dalam. Kota besar dengan gemerlap lampu sepanjang malam, aktivitas warga yang hampir tak pernah mati. Pesta diadakan dimana-mana, suara denting ‘tos’ gelas terdengar amat keras, barang dagang macam souvenir dan pakaian tersebar di setiap sudut kota. Namun yang mengenaskan, cerita lama yang tak pernah berakhir sampai kiamat pun berlangsung disana, orang-orang yang tak kenal batas angka dalam dompetnya yang hanya dapat menikmati terangnya Kota Burma, sedangkan warga lusuh hanya dapat melihat dari jendela kilaunya sepatu orang-orang di dalam restoran mahal. Air liur jadi santapan tiap malam mereka. Sebagai pusat ibu kota negara, masalah lingkungan selalu menjadi posisi paling atas di daftar catatan petugas kota, sampah bertebaran, gerobak dagang berderet tak karuan, parkir liar seperti biasa menjadi penyakit orang-orang. Saat itulah, seumur hidupnya, Orwell mempunyai posisi penting untuk membenci diri sendiri dan dibenci banyak orang.
***
Saya memacu sepeda motor dalam kecepatan sedang, melewati turunan Jalan Setiabudi untuk menuju pusat kota. Sampailah di persimpangan jalan, sorot lampu lalu-lintas dan penunjuk arah menunjukan jalur kanan menuju Jalan Cihampelas, daerah wisata yang menjadi salah satu destinasi turis ketika menyambangi Kota Bandung. Sepeda motor saya mulai melambat akibat kemacetan jalan, memasuki salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Bandung, Cihampelas. Spontan mata melirik kanan-kiri untuk melihat keadaan, sambil sedikit melamun, ingatan tentang kisah George Orwell ketika berada di Burma terlintas di pikiran; daerah ini sama semrawut dan memuakkannya. Sinar matahari tertutup oleh jembatan tak fungsi yang dibangun oleh pemerintah daerah, pedagang yang direlokasi masih ‘nakal’ menghalangi pematang jalan, orang-orang terlihat menyedihkan dengan barang bawaan yang amat banyak.
Setelah beberapa kilometer dilalui, sampailah di ujung Jalan Cihampelas. Terang matahari kembali terlihat, jari menekan pegangan rem karena lampu merah perempatan jalan di bawah Jembatan Pasopati menyala. Selain suara knalpot dari kendaraan lain, terdengar sayup suara yang lain. Saat saya diam memperhatikan kapan lampu hijau akan menyala, sontak mencari asal suara tersebut. Dentuman yang tak asing terdengar, saya melirik ke arah kanan, dimana ada satu area pemisah jalan yang lumayan luas, kumpulan pengamen jalanan sedang memulai aksinya. Saya cukup kaget ketika melihat formasi dengan format full band yang memainkannya, mulai dari set drum, dua gitar, bass, biola, dan tentunya satu vokalis yang paling depan.

Aba-aba dimulai dari ketukan drum, petikan gitar bersambut, volume mulai membesar ketika instrumen lain ikut bermain. Semakin kaget–dan kagum–ketika lagu yang dimainkan adalah “To Love Somebody” dari band legendaris asal Inggris, Bee Gees. Tak pikir panjang, sebelum lampu hijau menyala saya gas sepeda motor untuk menepi memarkirkannya di tepian gedung yang sudah tutup. Karena lampu hijau yang telah menyala, mereka hanya sempat memainkan setengah durasi dari lagu tersebut. Namun karena masih penasaran, saya sempatkan waktu untuk melihat ‘pertunjukan’ mereka selanjutnya. Sebatang rokok saya nyalakan, sambil menunggu kembali giliran lampu merah, saya perhatikan mereka sangat siap layaknya musisi “profesional” yang bermain diatas panggung besar. Ketika kendaraan kembali berhenti, pertunjukan dimulai, sekarang giliran lagu lokal yang dimainkan, salah satu setlist andalan God Bless, “Rumah Kita” dimainkan. Walau perangkat yang dipakai sangat terbatas, namun kekaguman saya tidak berkurang sedikitpun. Ini satu hal yang baru, musisi jalanan dengan persiapan dan peralatan yang sangat niat luar biasa.
Kadung penasaran dan kekaguman saya sudah sampai ujung kepala, saya memberanikan diri untuk menghampiri mereka saat rehat. Bertemulah dengan salah satu punggawa yang bertanggung jawab memegang kendali gitar, ia bernama Anwar. Dengan kaos Rolling Stone dan celana jeans lusuh, ia menerima sapaan saya dengan ramah. “Eh, A, punten ieu kalotor” ucap dia saat saya menyodorkan salam tinju untuk menyapa. Saya meminta waktu kepada Anwar untuk ngobrol, dengan santai ia bersedia, meninggalkan sebentar rekan-rekannya yang melanjutkan ‘tugas’ mereka menghibur para pengendara.
Saya ajak ia ke warung kopi di bawah jembatan, bertanya beberapa hal mengenai kegiatannya sebagai musisi jalanan. “Saya mulai jadi pengamen dari tahun 2010, dulu masih keliling ti angkot ka angkot,” kenangnya sambil menyeruput kopi yang kami pesan. Tak banyak bertele-tele, saya langsung sodorkan pertanyaan tentang kekaguman saya akan format yang mereka mainkan, set penuh semua aransemen dengan kelihaian pemainnya. “Pokokna setelah saya lama ngamen di angkot, saya mulai ketemu banyak temen sesama pengamen. Diajaklah ke perkumpulan pengamen di Bandung, kaleresan saya gabung yang di daerah Cihampelas, namanya KMJ (Komunitas Musisi Jalanan) Bandung. Hampir di setiap daerah di Bandung ada, pokokna tersebar KMJ teh, A.” pembicaraan tertunda beberapa detik untuk Anwar menyalakan rokoknya. “Pas sebelum pandemi, saya bareng yang lain yang gabung di KMJ jadi tempat kumpul buat pengamen, mulai dari sana kami ngobrol soal banyak hal.”
“Hayu ah, urang nyieun nu rada serius, make setelan band. Urang cicing weh di setopan.” ucap Deden, yang diaku sebagai kordinator KMJ. Dengan perangkat musik seadanya hasil dari urunan dan donasi dari seseorang yang tak mau Anwar sebut, mereka mulai berlatih dengan format band. Memainkan lagu populer, berdandan layaknya musisi profesional. “Kami ingin keliatan serius, A. ningalikeun pengamen ge bisa siga artis-artis nu lain.” tegas Anwar soal pertanyaan saya mengenai format mereka.
Satu hal yang membuat mereka semakin menarik ketika Anwar berkata bahwa mereka ingin betul-betul menghibur para pengendara jalan di perhentian lampu lalu-lintas dengan lebih serius, menampilkan permainan terbaik mereka. Anwar dan kawan-kawan di KMJ sepakat bahwa label pengamen yang sering ‘mengganggu’ ingin dihilangkan, itulah salah satu alasan utama mengapa Anwar–dan musisi jalanan Bandung di daerah lain–meningkatkan “kualitas” bermusiknya, mereka lelah dengan stigma masyarakat kepada musisi jalanan, mereka sadar derajat mereka mesti sama dengan yang lain. Bahwa tidak ada batasan kelas dalam mencari nafkah.
Itu semua berhasil, saya berani menjadi saksi. Mulai hari ini ketika ada format musisi jalanan seperti Anwar yang saya temukan di jalan, saya tak banyak mengeluh oleh padatnya kendaraan, mereka-lah obat pelipur di tengah rumitnya kota. Salah satu yang saya sadari, ketika kita harus menunggu akhir pekan untuk menyaksikan musisi di acara-acara panggung besar, hari-hari kita di jalanan pun sudah bisa ditemani oleh mereka, walau hanya beberapa saat. Mereka adalah The New Folk of Bandung Street Musician.
***
Kita penat dengan apa yang kita kerjakan setiap hari, menemukan banyak hal menjijikan yang diciptakan diri sendiri atau masyarakat, masalah kota yang tak kunjung usai. Saya pun merasa benci pada hidup, seperti Orwell ketika memegang laras panjang di Burma. Namun saya bisa sedikit tersenyum ketika menemukan hal yang diciptakan oleh Anwar dan grupnya memainkan lagu di tepian jalan, ternyata kutipan M.A.W Brower yang terkenal itu sudah tak menarik untuk disampaikan, Bandung saat ini bukan hanya diciptakan saat Tuhan tersenyum, namun ada pemeran lain, para pejuang tepi trotoar yang memainkan pesona nya, mereka menyalakan mesin kota untuk masyarakat agar dapat tersenyum di jalanan, Anwar beserta KMJ. Angkat topi dan bersulang untuk gelas kopi kepada mereka.
***
Artikel ini merupakan bagian dari seri “Adu Nasib Musisi Jalanan” yang meliput hiruk-pikuk musisi jalanan di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung dalam kolaborasi Highvolta Media dan Pamflet Generasi dengan tema payung “Orang Muda dan Ruang Publik”. Simak kisah musisi jalanan Jakarta dan Yogyakarta di sini.
Keluaran kolaboratif lainnya bisa dipantau melalui akun Instagram Highvolta Media (@highvolta_) dan Pamflet (@pamfletgenerasi).