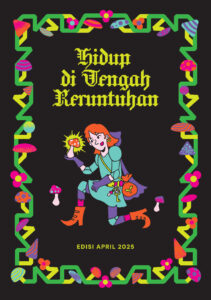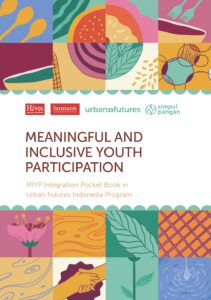“Tetapi saya mengatakan bahwa korban itu ada, saya menangani tiga orang dan salah satunya adalah anak berumur 14 tahun. Dan salah satu akibat dari perkosaan itu adalah ketiga-tiganya agak – seakan-akan—pikirannya hilang, tetapi yang paling nyata adalah anak yang berumur 14 tahun ini menjadi gila, agak gila..” [1]
Bisa jadi kita adalah anak-anak muda yang merasakan sendiri bagaimana di dalam sekolah, bangunan pengetahuan dan ingatan kita seputar tragedi 1998 berkisar di antara frasa-frasa seperti “Turunnya Soeharto”, “demonstrasi mahasiswa”, atau “krisis ekonomi”. Kita belajar dan menghapal nama-nama mahasiswa yang ditembak aparat, tempat-tempat kerusuhan meledak, sampai apa persisnya kata-kata Soeharto ketika ia memutuskan berhenti menjadi presiden. Namun kita sering lupa membahas lagi siapa sebenarnya kelompok yang karena mereka kita kini memiliki semacam jaminan dan perlindungan untuk bebas dari kekerasan: perempuan.
Pada bulan Agustus 1998, sebuah artikel berjudul “Siapa Dalang Perkosaan Massal?” dicabut dan batal terbit dari majalah Jakarta, Jakarta nomor 610. Artikel tersebut berisi wawancara bersama narasumber Romo I Sandyawan Sumardi S.J., atau Romo Sandy*), yang saat itu bekerja sebagai Sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Beberapa di antara pekerjaan yang dilakukan Romo Sandy adalah menemui keluarga korban tragedi 1998, termasuk juga para perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual. Lima tahun kemudian, artikel yang dicabut tersebut akhirnya diterbitkan dan dimuat dalam buku berjudul “Surat dari Palmerah”, yang sebenarnya merupakan kumpulan editorial yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma, pemimpin redaksi majalah Jakarta, Jakarta pada periode 1996-1999.
Faktanya, berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah usaha yang dulu amat sulit untuk dilakukan. Jika kita memikirkan kembali mengapa kekerasan terhadap perempuan dalam konteks peristiwa 1998, misalnya, kita akan teringat bagaimana kita diajarkan di sekolah bahwa kekerasan ini adalah dampak dari kesenjangan dan himpitan krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat, hingga akhirnya mendorong perilaku agresif yang salah satunya mewujud menjadi tindak pemerkosaan massal. Pemerkosaan massal ini terjadi secara spontan, sporadis dan tak terlacak oleh aparat. Di dalam masyarakat yang kerap memandang bahwa kejahatan dan kekerasan adalah suatu hal yang lumrah terjadi pada perempuan, runutan sebab akibat tersebut tidak sulit diterima, setidaknya bagi masyarakat secara umum. Namun kenapa artikel wawancara bersama Romo Sandy kemudian batal terbit?
Dalam artikel wawancara sepanjang enam halaman tersebut, kita akan tahu bagaimana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama Mei 1998 bukanlah suatu dampak atau rentetan kekerasan yang muncul secara serta merta, melainkan sebuah kejahatan yang sistematis dan terencana dengan perempuan sebagai kelompok yang dikorbankan demi kepentingan politik. Secara resmi, Data Tim Gabungan Pencari Fakta menyebutkan bahwa terdapat 52 orang korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual—namun ini hanya jumlah selama kerusuhan Mei terjadi, belum termasuk jumlah korban sebelum dan sesudah kerusuhan. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di tempat umum seperti di jalan atau di tempat-tempat usaha, tetapi juga di dalam rumah atau bangunan. Sebagian besar korban diperkosa oleh lebih dari satu orang pada satu waktu yang sama (gang rape) di hadapan orang lain, serta mayoritas korban adalah perempuan dari etnis Cina [2].
Selama melakukan investigasi dan mendampingi korban, Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat bagaimana pola pemerkosaan yang terjadi dan mengapa mayoritas korban merupakan perempuan dari etnis Cina. Hal ini diterangkan oleh Palupi, staf Divisi Pendataan dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dalam artikel yang sama dari majalah Jakarta, Jakarta. Awal pemerkosaan itu diawali dengan pengkondisian untuk menjadikan perempuan Cina menjadi target kebencian. Ada usaha-usaha orang yang berkeliling ke perkampungan miskin, mencari pemuda-pemuda yang diajak untuk melakukan pemerkosaan. Awalnya, mereka mentraktir pemuda-pemuda itu jajan, rokok dan minum, hingga kemudian sampai mereka akrab, mereka mengatakan, “Sebentar lagi kalian dapat barang-barang mewah dan perempuan-perempuan Cina yang selama ini elu nggak bisa jamah” [3].
Pada saat itu, di tengah situasi yang mencekam sepanjang Mei 1998, sekretariat Tim Relawan didatangi para pelapor sampai dengan 20-30 orang per harinya. Keberadaan sekretariat maupun posko-posko relawan seperti ini menjadi amat penting untuk perlindungan korban dan pengumpulan fakta. Pemerkosaan massal, misalnya, merupakan salah satu kasus yang faktanya sulit terungkap dan lamban ditangani oleh pemerintah karena faktanya dianggap simpang siur. Saat itu, data terkait pemerkosaan seperti siapa korbannya, dimana terjadinya, atau bahkan apakah benar ada perkosaan atau tidak, menjadi alasan mengapa pemerintah lamban bertindak menangani kejahatan yang menurut Romo Sandy merupakan “kebiadaban massal yang sistematis dan terorganisir” ini. Menurut beliau, tidak adanya pengaduan atau laporan ke pemerintah bukan berarti tidak adanya pemerkosaan. Sederhana saja, ujar beliau, sebab pemerintah abai kepada kondisi-kondisi seperti rasa malu, aib, beban fisik dan batin yang dirasakan oleh para perempuan yang menjadi korban maupun saksi mata dari pemerkosaan massal. Belum lagi ada teror yang dilakukan kepada para korban maupun para relawan pendamping. Romo Sandy bertutur bagaimana situasi para relawan ini hanya berbeda tipis dengan para korban kerusuhan dan perkosaan. Mereka juga diancam, diteror, bahkan dikirimi granat. Semua ini yang semakin meyakinkan Romo Sandy bahwa pemerkosaan dan kerusuhan didalangi oleh aktor(-aktor) yang sama, bahwa ada usaha untuk menutupi fakta dan meneror siapa saja yang berusaha mengungkapkan kebenaran [4].
Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tragedi mempersatukan umat manusia. Sekretariat Tim Relawan untuk Kemanusiaan mungkin menjadi saksi untuk itu. Di sinilah, ujar Romo Sandy, solidaritas korban dan empati terjalin, juga terbentuk konsolidasi perjuangan untuk melawan kekerasan terhadap sesama manusia. Tidak hanya Tim Relawan, saat itu para aktivis perempuan dan penggiat hak asasi manusia membentuk juga kelompok yang disebut Masyarakat Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. Kelompok ini tidak hanya mendampingi korban, tetapi juga berinisiatif untuk menemui Presiden Habibie dan menuntut agar Presiden mengutuk dan meminta maaf atas kejadian yang dialami korban kerusuhan, serta agar pemerintah segera melakukan investigasi independen dan mengadili para pelaku tindak kekerasan tersebut. Lewat perjuangan inilah Keputusan Presiden tanggal 15 Oktober 1998 lahir, yang merupakan instruksi untuk pembentukan sebuah komisi independen yang saat ini kita kenal dengan nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, atau Komnas Perempuan.
Teman-teman, melalui artikel wawancara bersama Romo Sandy yang syukurlah akhirnya dapat terbit dan kita baca tersebut, juga dengan membahas kembali kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama 1998, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan kembali secara lebih dalam. Salah satunya misalnya apakah kita, juga aparat dan masyarakat, telah memiliki sensitivitas terhadap perempuan sebagai korban kekerasan atau pun perkosaan. Kedua, apakah situasi saat ini sudah berubah? Bisa saja saat ini kita adalah anak-anak muda yang hidup dan tumbuh besar dalam masyarakat yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan kita tahu bahwa kita selalu bisa menuntut hak kita jika kita mengalami ketidakadilan dan kekerasan dalam bentuk apapun. Tapi bagaimana kita kemudian memaknai bahwa kekuasaan dan kepentingan politik dari seseorang atau suatu rezim, sewaktu-waktu, dapat memposisikan kita atau siapa saja sebagai korban? Bagaimana jika kita lah yang menjadi korban—akankah kita punya keberanian untuk bersuara? Dan bagaimana kita, sebagai anak muda yang menikmati buah perjuangan dari Romo Sandy dan tokoh-tokoh lainnya, yang tercatat atau pun tidak di buku sejarah kita, memiliki keberpihakan terhadap para korban dan orang-orang yang memperjuangkan agar hidup kita lebih layak?
Di atas itu semua, maukah kita semua melakukan sesuatu untuk memastikan agar segala bentuk kekerasan tidak terulang lagi?
Catatan Kaki:
[1] Kesaksian Ibu Edith Witoha, konselor, dalam http://kabarinews.com/kesaksian-kasus-perkosaan-mei-1998/31292. Laman ini memuat transkrip wawancara yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sembilan orang saksi yang melihat, mendengar dan membantu korban perkosaan pada Mei 1998.
[2]Data-data ini diambil dari Seri Dokumen Kunci “Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998”, diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada November 1999, yang dapat diunduh bebas dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/02/SDK-2-Temuan-Tim-Gabungan-Pencari-Fakta-Peristiwa-Kerusuhan-.pdf.
[3][4] Kutipan-kutipan wawancara ini dapat dibaca dalam kumpulan tulisan Seno Gumira Ajidarma, Surat dari Palmerah (Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), pada bagian “Dokumen Wawancara yang Tidak Disiarkan” halaman 272-285.
*) Tulisan ini dibuat pada tahun 2015, saat ini Sandyawan lebih memilih dipanggil Bapak setelah tidak lagi menjadi pastor Yesuit.