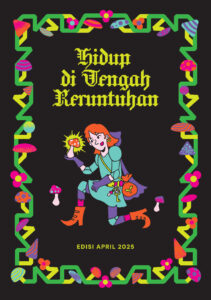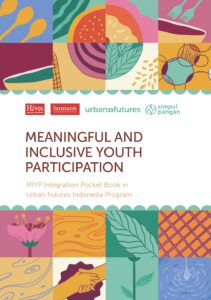Dalam dua bulan terakhir, gerakan Reformasi Dikorupsi menyadarkan kita bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ribuan mahasiswa, pelajar, buruh, dan berbagai elemen masyarakat sipil turun ke jalan untuk memperjuangkan demokrasi dan agenda pemberantasan korupsi. Namun, di tengah air mata, darah, dan keringat yang tumpah, media sosial malah ramai dengan berbagai opini yang mendiskreditkan perjuangan mereka.
Dua upaya mendiskreditkan gerakan Reformasi Dikorupsi bisa kita lihat melalui tersebarnya screenshot percakapan grup WhatsApp STM dan hoaks ambulan pengangkut batu untuk massa aksi. Kedua hal tersebut bertujuan untuk memanipulasi informasi, sehingga masyarakat tidak lagi bersimpati.
Melalui tulisan Information Manipulation Theory, Steven A. McCornack menjelaskan bahwa informasi dapat dimanipulasi sesuai permintaan dan situasi kompleks. Dalam teori tersebut, dijelaskan pula bahwa manipulasi informasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang telah terencana.
Manipulasi informasi dilakukan dengan menyebarkan informasi yang bersifat memanipulasi (deceptive). McCornack menyebutkan terdapat berbagai jenis pesan manipulatif, yakni pemalsuan (falsification) yang menolak validitas informasi yang benar; distorsi (distortion) yang dilakukan dengan melebihkan, meminimalisir, dan pengelakan; serta penghilangan (omission) yang dilakukan dengan menghilangkan referensi-referensi yang relevan.
Upaya manipulasi informasi tentu bukanlah sesuatu yang baru, laporan Oxford Internet Institute berjudul The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation mengungkapkan bahwa upaya manipulasi di media sosial yang terorganisasi di 70 negara pada 2019 meningkat 150% dalam 2 tahun terakhir.
Upaya manipulasi informasi ini dilakukan dengan memanfaatkan akun-akun palsu yang dapat dengan mudah dibuat di media sosial. Umumnya akun-akun palsu ini dioperasikan oleh manusia, bot, dan cyborg untuk menyebarkan informasi. Di 70 negara yang diteliti, setidaknya 60 negara ditemukan akun-akun palsu yang dioperasikan oleh manusia, termasuk Indonesia.
Bahkan, diketahui bahwa penyebar informasi biasanya menggunakan akun palsu dalam mengelola halaman, menyebarkan konten, serta menggiring opini masyarakat di dunia maya. Para manipulator ini dikenal dengan istilah cyber troops, yaitu aktor pemerintah atau partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik melalui media sosial.
Nah di Indonesia, para manipulator ini kita kenal dengan istilah buzzer, yang merupakan individu atau akun yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi, baik karena dibayar atau secara sukarela. Mereka memiliki banyak pengikut di dunia maya yang bisa dengan mudah digerakkan.
Fenomena buzzer paling marak terjadi di Twitter dan biasanya menggunakan beragam strategi, salah satunya adalah dengan menggunakan akun bot secara massif dengan memanfaatkan otomasi mesin dan algoritma media sosial, sehingga menghasilkan kicauan dengan frekuensi tinggi dan bisa menjadi trending topic.
Selain itu, buzzer juga biasanya bergerak secara berkelompok untuk menyebarkan informasi. Biasanya dilakukan dengan menempatkan dua atau lebih akun untuk terlibat dalam suatu percakapan, dengan berbagi peran antara yang pro dan kontra. Strategi ini efektif untuk memunculkan rasa penasaran netizen, sehingga mendapatkan perhatian yang luas.
Selain melalui media sosial, buzzer bisa menyebarkan pesan tersebut melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Biasanya buzzer tergabung dalam banyak grup yang dalam setiap grup terdapat lebih dari ratusan anggota.
Didukung kemampuan produksi konten, jaringan luas, serta kemampuan memviralkan sebuah pesan dengan cepat. Jadilah para buzzer ini memiliki banyak followers yang setuju terhadap narasi yang disebarkan buzzer.
Tidak heran banyak netizen di Indonesia yang sangat bias dalam melihat suatu persoalan karena seringnya terpapar informasi yang keliru namun sesuai dengan pemikiran atau harapan mereka. Hal ini akhirnya membuat daya kritis mereka semakin terkikis.
Selain itu, buzzer biasanya juga melakukan berbagai hal lain agar agendanya tercapai, seperti melaporkan akun secara massal, melakukan trolling, doxing dan melakukan pelecehan. Hal ini tentu saja sangat efektif untuk membungkam lawan mereka dan membuat mereka seolah tidak tersentuh oleh berbagai opini lain yang kritis.
Bisingnya dengungan para buzzer ini pada akhirnya menurunkan kualitas ruang publik dan demokrasi, terutama di Indonesia. Fabrikasi percakapan, perang tagar serta disinformasi yang diproduksi oleh para buzzer dapat menimbulkan distorsi di ruang publik, yang paling parah adalah mengaburkan batas antara aspirasi publik dengan aspirasi rekaan dari pihak yang membayar mereka.
Tentu saja fenomena buzzer ini adalah paradox dari demokrasi kita yang semakin terkebiri. Namun bukan berarti kita harus diam saja dan menjadikan mereka sebagai bahan bergunjing. Kita bisa tetap mengeluarkan opini kita sembari mengedukasi publik sehingga masyarakat bisa melakukan cek fakta dan verifikasi informasi secara mandiri. Dan narasi Reformasi Dikorupsi tidak lagi dikebiri oleh distorsi informasi yang telah dimanipulasi.