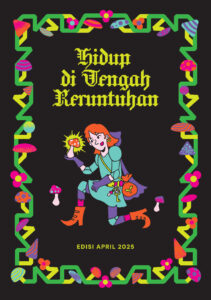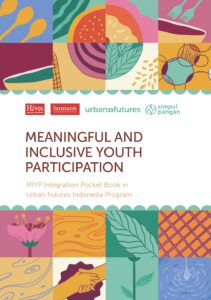Pada 6 Maret 2020 lalu, Komnas Perempuan mengeluarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dari catatan tersebut, Komnas Perempuan menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencapai angka 11.105 kasus atau sebanyak 75%, lalu disusul kekerasan di ranah publik sebanyak 3.602 atau 24%. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, disusul kekerasan seksual, psikis dan ekonomi. Sementara di ranah publik, bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan adalah pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.
Belakangan ini, kita mendapati semakin banyak pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus ini datang dari berbagai sektor, dari lingkungan universitas, sekolah, industri, kelompok seniman, bahkan dari komunitas aktivis.
Mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan begitu marak terjadi? Apa yang membuatnya terus ada dan langgeng dalam kehidupan kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu dulu bagaimana kekerasan bekerja.
Apa itu Kekerasan?
Saat ingin mengartikan kekerasan, mungkin hal yang muncul di benak kita adalah tindakan memukul atau melukai orang lain dengan atau tanpa senjata. Kekerasan biasanya diartikan sebagai tindakan yang menyakiti tubuh, pikiran, atau jiwa seseorang. Pada tahun 1969, seorang peneliti perdamaian dari Norwegia, Johan Galtung, memperkenalkan tiga jenis kekerasan: langsung, struktural, dan kultural. Galtung menggambarkan ketiganya dalam bentuk segitiga kekerasan. Mereka saling berkaitan satu sama lain.
Selama ini, mungkin kita masih hanya kenal dengan kekerasan langsung. Ia adalah bentuk kekerasan yang paling mudah diamati, karena tampak dalam bentuk perbuatan fisik, verbal, maupun psikis. Efeknya juga dapat dirasakan secara langsung oleh pihak yang menerima, misalnya pemukulan, penganiayaan, perundungan, pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Sementara itu, kekerasan struktural dan kultural lebih sulit diamati karena dampaknya tidak terlihat secara langsung. Namun, kerap kali kekerasan struktural dan kultural lah yang menopang langgengnya kekerasan langsung. Seperti gunung es, kekerasan langsung berada di puncak segitiga kekerasan, sedangkan kekerasan struktural dan kultural berada di bawah permukaan sehingga kerap tidak kita sadari.
Yang dimaksud dengan kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang terjadi secara sistemik dan melembaga. Ia terwujud misalnya dalam bentuk kebijakan negara yang mendiskriminasi gender tertentu, kurikulum pendidikan yang tidak inklusif terhadap minoritas gender, atau sistem ekonomi yang eksploitatif dan menyengsarakan terutama bagi buruh perempuan. Kekerasan struktural berperan besar dalam membentuk dan memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa. Ia seringkali membuat kelompok seperti perempuan dan minoritas gender berada di posisi bawah sehingga rentan menjadi sasaran kekerasan.
Kekerasan kultural terwujud dalam nilai dan norma yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang disampaikan melalui agama, adat istiadat, ideologi, maupun ilmu pengetahuan. Nilai dan norma ini biasanya mengajarkan kita tentang apa yang benar dan salah, mana yang suci dan hina, atau mana yang normal dan tidak normal. Mereka diartikan sebagai kekerasan kultural saat membuat kita berpikir bahwa kekerasan langsung dan struktural adalah hal yang benar, normal, atau bahkan perlu dilakukan.
Bagaimana kekerasan yang dialami perempuan dipahami menggunakan konsep segitiga kekerasan ini?
Kekerasan langsung yang dialami perempuan dan minoritas gender di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konteks struktur dan kultur yang mendukungnya. Ia dimungkinkan dan dilanggengkan oleh aspek struktural dan kultural di sekitarnya. Hanya dengan melihat aspek struktur dan kulturlah kita bisa memahami mengapa kekerasan terhadap perempuan terus ada dan bahkan terus meningkat.
Kekerasan Kultural
Perempuan Indonesia hidup di bawah budaya patriarki yang begitu kuat. Budaya ini mengatur bagaimana perempuan yang baik dan ideal, dari mulai cara berpakaian, bertutur, bertindak dari sudut pandang yang maskulin. Apabila tidak memenuhi standar tersebut, mereka akan dicap sebagai perempuan yang tidak baik. Di saat yang sama, laki-laki dituntut harus menjadi sosok yang kuat dan memiliki kuasa. Laki-laki yang tidak memenuhi standar maskulinitas ideal pun akan dicap sebagai “kurang laki-laki”. Semua standar ditentukan berdasarkan kadar maskulinitas. Budaya kita begitu mengagungkan maskulinitas, yang pada akhirnya harus menunjukkan ekspresi kuasa dengan menyakiti mereka yang tidak maskulin. Ajaran-ajaran ini tertanam dalam pikiran kita sejak kecil dan selalu hadir di berbagai aspek budaya, sehingga sulit untuk dihapuskan.
Dalam hal kekerasan seksual, berbagai ajaran budaya patriarki tadi membuat kita seringkali mewajarkan saat laki-laki menjadi pelaku. “Boys will be boys” atau “namanya juga laki-laki” adalah contoh ungkapan yang tidak jarang terucap dalam merespon kekerasan seksual yang mereka lakukan. Mereka punya hasrat yang tidak tertahankan sebagai lelaki sejati. Maka, tidak heran apabila perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering diberi pertanyaan-pertanyaan menyudutkan untuk membuktikan kebenaran. Mereka harus dipastikan terlebih dahulu tidak memakai pakaian yang terbuka, atau memberi sinyal yang membuat laki-laki tergoda. Pada akhirnya, perempuan juga kerap disalahkan karena tidak bisa menjaga “kesuciannya.”
Salah satu konsep populer yang sering dipakai dalam menjelaskan hubungan kekerasan kultural dengan kekerasan seksual adalah rape culture atau budaya perkosaan. Konsep ini menjelaskan tingkatan kekerasan seksual dalam bentuk piramida, yang pada level terbawah diawali dengan candaan-candaan seksis, homofobik, atau transfobik. Diawali dari candaan seksis yang diwajarkan, kekerasan ini meningkat menjadi pelecehan, ancaman kekerasan, hingga pemerkosaan dan pembunuhan (femisida). Kebiasaan kita mewajarkan candaan-candaan seksis dari hari ke hari, menjadi bibit awal untuk mewajarkan kekerasan seksual.
Kekerasan Struktural
Di Indonesia, terdapat banyak sekali produk kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas gender. Komnas Perempuan mencatat, terdapat setidaknya 421 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Beberapa di antaranya adalah peraturan yang membatasi ruang gerak perempuan melalui tata cara berpakaian hingga penetapan jam malam. Peraturan ini tidak muncul begitu saja. Ia merupakan produk dari ide dan nilai masyarakat yang patriarkis.
Selain banyaknya peraturan diskriminatif terhadap perempuan, pemerintah kita juga begitu lambat dalam proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Padahal, RUU ini dibuat untuk menjamin perlindungan bagi penyintas kekerasan seksual dan mengatur sistem peradilan bagi pelaku yang mencakup kewajiban rehabilitasi.
Kenapa RUU PKS begitu penting? Indonesia saat ini masih belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menindak kasus kekerasan seksual. Pendefinisian “pemerkosaan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya sebagai penetrasi penis ke vagina, dan pemaksaan fisik. Definisi ini abai terhadap pengalaman penyintas yang mengalami kekerasan seksual lainnya yang juga tak kalah serius. Komnas Perempuan mendefinisikan 15 jenis kekerasan seksual, yang nantinya akan dimuat di dalam RUU PKS. Ketiadaan payung hukum yang jelas, membuat penyintas kekerasan seksual seringkali urung dalam melaporkan kasus yang terjadi. Padahal, kalau kasus-kasus ini tidak diungkap malah akan memberi pelaku rasa impunitas dan memungkinkan terulangnya kasus yang sama dan bertambahnya korban.
Kekerasan terhadap perempuan, seperti yang tergambar dalam CATAHU Komnas Perempuan tahun ini akan terus terjadi apabila kita tetap membiarkan budaya yang menormalisasi kekerasan dan hukum yang diskriminatif diberlakukan di dalam masyarakat. Kedua aspek ini, struktural dan kultural menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan. Oleh karenanya, kita harus peka terhadap berbagai wujud budaya dan struktur yang melanggengkan kekerasan dan tidak malah menjadi bagian di dalamnya dengan diam dan membiarkan kekerasan terus terjadi.
Referensi: