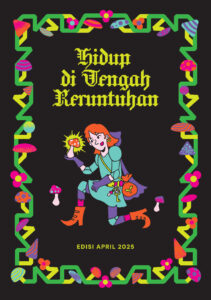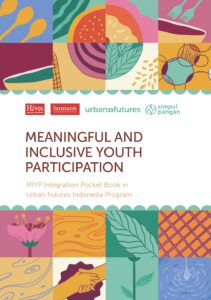Kiki Febriyanti membutuhkan waktu empat bulan, bersama timnya, melakukan riset untuk film dokumenter berjudul Calalai in-Betweenness. Film yang diproduksi bersama Hivos SEA, Ardhanary Instititute, dan Rumah Pohon ini berkisah tentang eksistensi perempuan dengan ekspresi gender maskulin di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep.
Film ini memberikan gambaran tentang pemahaman masyarakat Bugis mengenai konsep gender. Pemahaman ini berlandaskan pada naskah I Lagaligo yang menyatakan bahwa terdapat lima gender di dalam kehidupan manusia, yaitu Uruane (laki-laki), Makunrai (perempuan), Calalai (perempuan yang maskulin), Calabai (laki-laki yang feminin), dan Bissu (orang suci yang melampaui laki-laki dan perempuan).
Kelima gender di Bugis menurut Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Nurhayati Rahman, merupakan ajaran dalam I Lagaligo yang membagi kehidupan menjadi tiga dunia, yaitu Botti Langi’ sebagai perlambangan maskulinitas, Buri’ Liu sebagai perlambangan feminitas, dan dunia di tengahnya yang merupakan perkawinan dari dua dunia tersebut, yang melambangkan keseimbangan.
Melalui film ini Kiki menyajikan kepada penontonnya kekayaan dan kedalaman toleransi dalam masyarakat Bugis yang penting untuk diterapkan di Indonesia. Untuk lebih mendalami tentang film Calalai in-Betweenness, Pamflet mewawancarai Kiki untuk mencari tahu gagasan apa yang ingin disampaikan dan tujuan apa yang ingin digapai.
Pamflet: Kenapa fokus mengangkat tentang Calalai? Padahal yang banyak diangkat oleh akademisi ataupun pekerja kreatif lain adalah Bissu yang memang melampaui konsep tentang gender?
Pertama, semua ini berangkat dari pemahamanku yang menganggap bahwa manusia pada hakikatnya beragam, semua makhluk hidup berbeda-beda. Tanpa pemahaman ini mungkin waktu aku ditawari untuk menjadi sutradara film ini aku akan menolak. Lalu, kalo aku sendiri awalnya enggak tahu tentang Calalai, tahunya Bissu, karena Bissu memang sangat populer dan banyak yang membahas karena peran istimewanya di dalam masyarakat, seperti memimpin upacara-upacara sakral masyarakat Bugis.
Ketika aku diberitahu tentang Calalai tentu saja aku langsung tertarik, karena dalam masyarakat manapun, di dunia yang patriarki ini, perempuan masih jarang dibahas dan diberikan ruang untuk berbicara. Jadi Calalai menurutku menjadi hal yang penting untuk diangkat, karena secara biologis adalah perempuan, akan tetapi di masyarakat Bugis bisa menjalankan peran-peran maskulin atau peran-peran yang dianggap hanya bisa dijalankan oleh laki-laki sebagai pekerja di sektor publik, misal jadi pekerja bangunan, supir, camat, bupati, dan lain sebagainya.
Aku juga merasa bahwa masyarakat Bugis itu sangat maju pemikirannya, yang mana perempuan boleh juga untuk masuk ke ranah-ranah publik, yang menurut pandangan umum tidak layak dimasuki oleh perempuan. Selain itu, mereka juga sudah paham mengenai gender, mereka bisa membedakan antara gender dan jenis kelamin. Alasan-alasan itulah yang membuatku tertarik untuk mengangkat tentang kebudayaan Bugis, khususnya Calalai yang melampaui konsep umum tentang perempuan.
Pamflet: Ada enggak sih hal menarik waktu riset awal? Atau mungkin tetap ada enggak sih diskriminasi gender di sana?
Selama aku riset di Kabupaten Pangkep, aku belum pernah mendengar ada kasus diskriminasi terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin hal yang menurutku menarik dengan kacamataku sebagai orang Jawa adalah sangat berbaurnya perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari.
Gampangnya gini, warung kopi kan identik dengan laki-laki, seperti untuk tempat nongkrong ataupun sarapan, sedangkan perempuan berdasarkan stereotipnya di rumah, bersih-bersih, mengurus anak, dan tidak keluar rumah. Tapi ketika aku disana, ketika pagi semua orang berkumpul bersama di warung kopi dengan sangat biasa, laki-laki dan perempuan ngobrol seperti biasa, setelah sarapan dan ngopi mereka berangkat kerja masing-masing. Semua sangat natural dan hal tersebut bukan hal aneh untuk mereka.
Pamflet: Bagaimana proses pendidikan kepada perempuan hingga terbentuk kepribadian yang maskulin? Apakah hal itu diajarkan atau terjadi secara natural?
Menurutku proses pembentukan kepribadian anak untuk menjadi Calalai itu sangat natural dan tidak ada yang mengajarkan. Aku rasa setiap orang di sana memiliki kebebasan untuk menjadi maskulin atau feminim, karena hal tersebut tidak dilarang dan bukan hal yang tabu untuk dipilih. Saat aku riset, aku malah menemukan suami istri yang menjadi tukang bangunan, yang mana malah istrinya yang lebih jago mengolah pasir dan semen dibanding suaminya.
Pamflet: Lalu bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Calalai? Sempat kesulitan enggak sih waktu dulu mencari Calalai saat riset?
Saat aku riset dan mencari Calalai itu sangat mudah. Orang gampang aja menunjuk dan memberi tahu siapa yang Calalai di sekitar mereka. Baik ustadz, polisi, atau pegawai-pegawai itu sangat biasa untuk membahas soal keragaman gender. Seperti saat aku pergi ke toko bangunan, saat aku ngobrol sama pemiliknya yang seorang haji, aku inget ia ngomong kalo ia tidak mempermasalahkan soal Calalai, Calabai, ataupun Bissu, karena yang penting sesama manusia tidak saling mengganggu, jadi ingin seperti apa seseorang, itu adalah pilihan pribadi.
Menurutku, semua itu terjadi bukan karena teori-teori ilmiah, tapi karena memang sudah menjadi keseharian mereka. Mungkin bagi mereka, apa yang mereka lakukan bukanlah soal toleransi, tapi soal menghargai semua jenis ciptaan tuhan. Bagi kita toleransi membahas soal menerima perbedaan, tapi disana bahkan hal tersebut bukanlah hal yang dianggap berbeda. Masyarakat Bugis sudah melampaui konsep toleransi yang kita miliki.
Pamflet: Selain itu, ada enggak ekspresi kebudayaan lain yang mengajarkan soal nilai-nilai kesetaraan?
Nah, ada nih satu hal yang menarik dalam upacara pernikahan, yang mana ternyata nilai-nilai kesetaraan diajarkan sebelum pernikahan dilaksanakan. Saat aku di sana kebetulan sedang ada upacara pernikahan, dan saat ke dapur aku melihat di situ ada satu laki-laki di antara perempuan-perempuan yang sedang menyiapkan makanan. Laki-laki itu menyiapkan kue, makanan, dan segala macam untuk keperluan pernikahan. Terus aku tanya dong, dan ternyata laki-laki itu adalah calon pengantin laki-laki.
Calon pengantin laki-laki itu, ada di dapur untuk membantu ibu dan keluarga perempuan. Hal itu dilakukan supaya setelah menikah ia paham bahwa pekerjaan sebagai istri itu tidak mudah, terutama ketika sang istri sudah memiliki anak, sehingga dia akan menghormati istrinya. Itu adalah tradisi dan hingga hari ini aku belum menemukannya di daerah lain.
Ada juga bentuk kontrol sosial untuk laki-laki yang menurutku menarik. Jadi di Bugis itu perempuan punya hak untuk protes kepada suaminya jika tidak mendapatkan keadilan. Misalkan sang suami tidak menafkahi secara lahir ataupun batin, atau sang suami suka foya-foya, istri bisa protes dengan cara tidak menyajikan makanan dan minuman kepada teman suami yang sedang bertamu. Cara ini sudah menjadi kode adat yang diketahui secara luas, jadi sang suami akan malu pada temannya itu.
Pamflet: Nah balik lagi soal filmmu, waktu pemutaran di berbagai daerah, ada hal menarik menurut kamu menarik enggak?
Tentu saja ada. Mayoritas di pemutaran-pemutaran justru yang menonton bukan aktivis atau akdemisi, malah lebih banyak masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar. Sejujurnya aku lebih senang seperti itu karena tujuan untuk menyasar orang awam lebih tercapai. Setiap kali pemutaran anehnya selalu ada aja orang Bugis yang nonton dan sebagian besar belum tahu soal Calalai. Aku senang dengan hal ini, artinya aku menyambung rantai budaya yang terputus kepada anak muda Indonesia.
Pernah juga ada satu penonton yang mengaku selama ini bingung dengan identitas gendernya, namun setelah menonton film ini mengaku bisa menentukan identitas gendernya menurut keinginannya sendiri. Menariknya dia mengakui hal ini saat diskusi setelah pemutaran film.
Ketika pemutaran di luar Indonesia, banyak yang kaget dengan kekayaan budaya Indonesia yang mana mengakui adanya lima gender. Karena mereka selama ini hanya terpapar dengan berita buruk yang disampaikan oleh media. Selain itu mereka juga selama ini melihat budaya Indonesia hanya merujuk pada Bali.
Pamflet: Nah berbicara soal anak muda, ada enggak sih pesanmu untuk mereka?
Tentu saja aku berharap nilai-nilai budaya Bugis yang aku angkat dalam film ini tidak terputus di orang-orang tua saja. Aku berharap anak muda juga mampu menjadi penyambung rantai yang selama ini mulai terkikis dengan kemajuan zaman. Belajar dari teori-teori negara Barat memang penting, tapi lebih penting menggali kearifan budaya lokal untuk menjadi dasar nilai dalam menjalani hidup.
Aku juga berharap film ini menjadi pemicu dari banyaknya karya kreatif yang mengangat budaya lokal karena aku merasa Calalai in-Betweenness masih berada di permukaan budaya Indonesia yang begitu kaya. Jadi penting untuk terus menggali kearifan dan nilai-nilai untuk Indonesia. Film ini juga menurutku adalah pintu pembuka, dan aku juga ingin mendalami lagi untuk membuat karya tentang budaya Bugis.