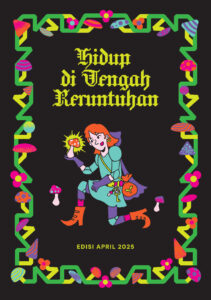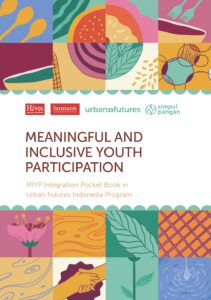Di dua hari belakangan ini, layar gawaiku dipenuhi dengan serba-serbi perayaan Hari Kartini dan Hari Bumi. Ini membuatku banyak berefleksi mengenai apa makna dari perjuangan Kartini untukku dan juga makna dari upaya segelintir orang yang merayakan bumi. Aku lantas sadar bahwa kedua topik ini merupakan sesuatu yang saling terkait dengan erat di dalam diriku. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarku–seperti hiruk-pikuk serangkaian kegiatan Women’s March Jakarta dan serangkaian manifestasi krisis ekologi yang belakangan terlihat dalam hadirnya banyak bencana, kehadiran isu perempuan dan alam dalam keseharianku ternyata menjadi peristiwa yang kucerna secara padu.
Untuk itu, aku ingin sedikit bercerita lebih jauh mengenai perempuan dan alam. Mari mulai dengan terjun lebih jauh ke dalam beberapa pengalaman yang menubuh, lalu perlahan-lahan menuju ke kesadaran akan benang merah antara perempuan dan lingkungan.
Melihat Patriarki di dalam Tubuhku
Selama masa kecil, perlakuan orang dewasa yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuanlah yang membuatku menyadari adanya seksisme dan patriarki. (Walau tentu aku tidak begitu piawai dalam menyebut apa yang aku alami dan amati ketika kecil dulu.) Di ingatanku, teman-teman lelaki akan bermain bola dengan riang di lapangan kecil Sekolah Dasarku, sementara teman-teman perempuan mencuci gelas-gelas teh dan piring-piring kecil yang dipakai para guru. Di ingatanku, ketika aku mengungkapkan keinginanku untuk bermain mobil-mobilan, ibuku menolak dan meninggalkanku yang bermain masak-masakan di halaman. “Tidak, itu adalah mainan laki-laki,” ungkapnya. Dari sini dan banyak pengalaman lainnya, aku tidak merasa lebih ‘kerdil,’ tapi aku dengan jelas merasa berbeda sebagai anak kecil yang berjenis kelamin perempuan.
Pikiran itu ternyata berubah seiring aku bertumbuh sebagai anak muda. Pubertas membuat tubuhku semakin meneriakkan jenis kelaminku: “Aku adalah seorang ‘anak gadis.’” Aku adalah seorang ‘anak gadis’ yang diajarkan untuk mempunyai rasa malu, harus bisa menjaga diri, terampil dalam pekerjaan rumah, dan bersikap patuh.
Banyak sekali petuah-petuah mengenai tubuhku yang kuterima dari orang tua di sekitarku; seperti mengenai posisi duduk dan berjalan yang tidak boleh mengangkang, penggunaan bra yang wajib karena katanya payudaraku akan kendor (dan bagaimana kendornya sepasang lemak dan kelenjar susu dianggap ‘buruk’), bagaimana luruhnya sel telurku melalui menstruasi ternyata merupakan sesuatu yang dianggap sangat kotor dan menjijikan, perawatan kulit yang harus kulakukan karena katanya kecantikan fisik merupakan aset perempuan, dan beribu ajaran lainnya yang didengar langsung oleh kupingku ini. Belum lagi narasi-narasi mengenai perempuan yang kudengar dari produk-produk budaya seperti film, iklan, dan lagu; ataupun yang tersirat dari perilaku sesama anak muda.
Perbedaan-perbedaan yang aku rasakan perlahan menjadi beban–seperti rantai di salah satu kakiku yang tersambung dengan bola besi dan lantas memberatkan setiap langkahku. Dan, parahnya lagi, aku sendiri memberikan izin dan ikut membantu mewujudkan rantai besi tersebut. (Jika kamu tumbuh berkembang dengan beribu narasi dan perilaku yang mencerminkan perempuan sebagai objek patuh yang berkodrat domestik, narasi tersebut akan membekas di dalam dirimu dan menubuh. Lihat saja Kartini dan upaya pembebasan perempuannya yang sekarang sering dinegasikan menjadi perayaan simbolik saja, seperti dengan penggunaan baju kebaya dan lomba memasak.)
Aku kemudian sadar bahwa perempuan memang mengalami penindasan dan diberikan sangat sedikit otonomi atas tubuhnya. Alih-alih otonomi, tubuh perempuanku ini adalah ranah politik. Tubuh perempuanku adalah tempat bermain yang memastikan bahwa the Patriarch masih mempunyai kuasa tertinggi.
Melihat Kapitalisme di Tubuh Bumi
Berangkat dari sini, aku kemudian melihat pengalaman yang sama pada alam. Aku selalu berpikir bahwa tanah coklat-kehitaman adalah rahim yang membuat kelahiran menjadi suatu yang lumrah. Bahwa air dan tumbuh-tumbuhan, yang menghidupi segala, selaras dengan peran yang disematkan pada seorang ibu. Bahwa fase bulan saja juga kutampung dalam tubuhku–berwujud siklus menstruasi yang datang dengan pergantian hormon dan tetek bengeknya.
Lantas, jika aku melihat alam sebagai tubuh perempuan, krisis ekologi semakin menjadi-jadi karena tubuh Ibu Bumi juga menjadi tempat bermain. Tubuh Ibu Bumi menjadi tempat bermain yang memastikan bahwa patriarki dan kapitalisme masih berkuasa dan bisa terus berjalan.
Kesadaran yang mungkin juga muncul dalam benak perempuan-perempuan lainnya dengan begitu organik ini kemudian lebih mudah kupahami ketika aku membaca tentang ekofeminisme. Menurut paham ekofeminisme pada umumnya, perempuan dan alam berbagi relasi yang sama terhadap laki-laki, yakni relasi yang bersifat subordinate atau lebih inferior dan instrumental–berfungsi sebagai alat. Terdapat logika mengenai dominasi yang begitu kental di relasi ini. Jika untuk perempuan dominasi ini terwujud dalam perempuan sebagai the second sex yang kehadirannya mendukung keseharian laki-laki dengan mengandung dan mengasuh; dominasi ini terwujud untuk alam dalam bentuk serangkaian kegiatan ekstraktif yang menjadi sistemik dan diwajarkan dengan mendarah-dagingnya pencarian keuntungan untuk manusia.
Hal ini semakin aku percayai ketika melihat, misalnya, hutan adat Kinipan–dan nilai-nilai budaya yang melekat di hutan adat ini–harus terenggut oleh perusahaan sawit yang selalu ingin mempunyai lebih banyak lahan dan penghasilan. Atau ketika melihat serangkaian bencana terkait siklon seroja di NTT yang besar kemungkinan bisa hadir lagi dengan dampak lebih besar jika alih lahan untuk tambang, sawit, dan wisata terus terjadi. Atau ketika melihat warga di Desa Wadas, Purworejo, yang sekarang sedang mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat karena menolak hadirnya perusahaan tambang dan pembangunan bendung yang sepihak. Krisis ekologi semakin terasa dampaknya, namun alam masih sekadar dilihat sebagai alat untuk mencari keuntungan.
Aku kira sejauh ini suatu perbedaan antara perempuan dan alam yang kurasakan adalah bahwa suara Ibu Bumi lebih pelan dan susah untuk didengar. Jika cerita-cerita dan desakan terkait penindasan perempuan bisa terdengar dengan lantang di berbagai gerakan, kampanye, serta suara perempuan itu sendiri; alam berbicara dengan bahasa yang berbeda. Desakan untuk menghentikan eksploitasi dan dominasi disuarakan oleh alam melalui krisis ekologi itu sendiri. Desakan itu disuarakan dengan hadirnya pandemi, gagal panen, bencana alam, naiknya suhu bumi, berkurangnya keanekaragaman hayati secara drastis, dan lainya yang merupakan reaksi dari ekosistem yang tidak stabil. Dan, tentunya, ketidakstabilan ini datang dari aku, kamu, dan ekonomi ekstraktif yang dibawa kapitalisme.
Sialnya, bahasa ini paling kentara dirasakan oleh petani, masyarakat adat, warga di negara-negara berkembang, dan bukan oleh segelintir elit yang berkuasa. Segelintir elit ini tidak tersentuh langsung oleh krisis ekologi–dan lantas tidak mendengar suara alam, karena mereka dilindungi ‘benteng’ yang dibangun dari keuntungan material yang selama ini dikumpulkan melalui partisipasi aktif mereka dalam eksploitasi alam.
Pada intinya, aku merasa lebih mudah untuk memahami gentingnya krisis ekologi karena identitasku sebagai perempuan. Aku lalu merasa harus mendorong perubahan, khususnya bagi alam yang semakin terancam dan enggan untuk didengar. Aku ingin berperan bukan saja sebagai perempuan, tapi juga sebagai anak muda yang masa depannya terancam. Apakah kamu juga merasa pernah mengalami penindasan, entah dalam bentuk apapun? Apakah kamu berempati dengan apa yang dialami bumi? Lalu, untuk menanyakan sesuatu yang lebih berarti dan sulit untuk dijawab, apa yang kemudian akan kamu (dan aku) lakukan?
Referensi:
Arumingtiyas, L. dan Saturi, S. ‘Bencana Datang, Di Tengah Orang Kinipan Terhalang Jaga Hutan Adat’. Mongabay, 15 September 2020. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/09/15/bencana-datang-di-tengah-orang-kinipan-terhalang-jaga-hutan-adat/
Egis, R. ‘Wadon Wadas Tuntut BBWSSO Cabut Izin Tambang di Desa Wadas’. Ekspresi Online, 9 April 2021. Diakses dari https://ekspresionline.com/wadon-wadas-tuntut-bbwsso-cabut-izin-tambang-di-desa-wadas/
Irfani, F. ‘Siklon Seroja Bukan Terakhir jika Krisis Iklim tak Segera Ditangani’. Tirto, 22 April 2021. Diakses dari https://tirto.id/siklon-seroja-bukan-terakhir-jika-krisis-iklim-tak-segera-ditangani-gdk5
Longenecker, M. (1997). Women, Ecology, and the Environment: An Introduction. NWSA Journal, 9 (3), 1-17. Diakses dari http://www.jstor.org/stable/4316527