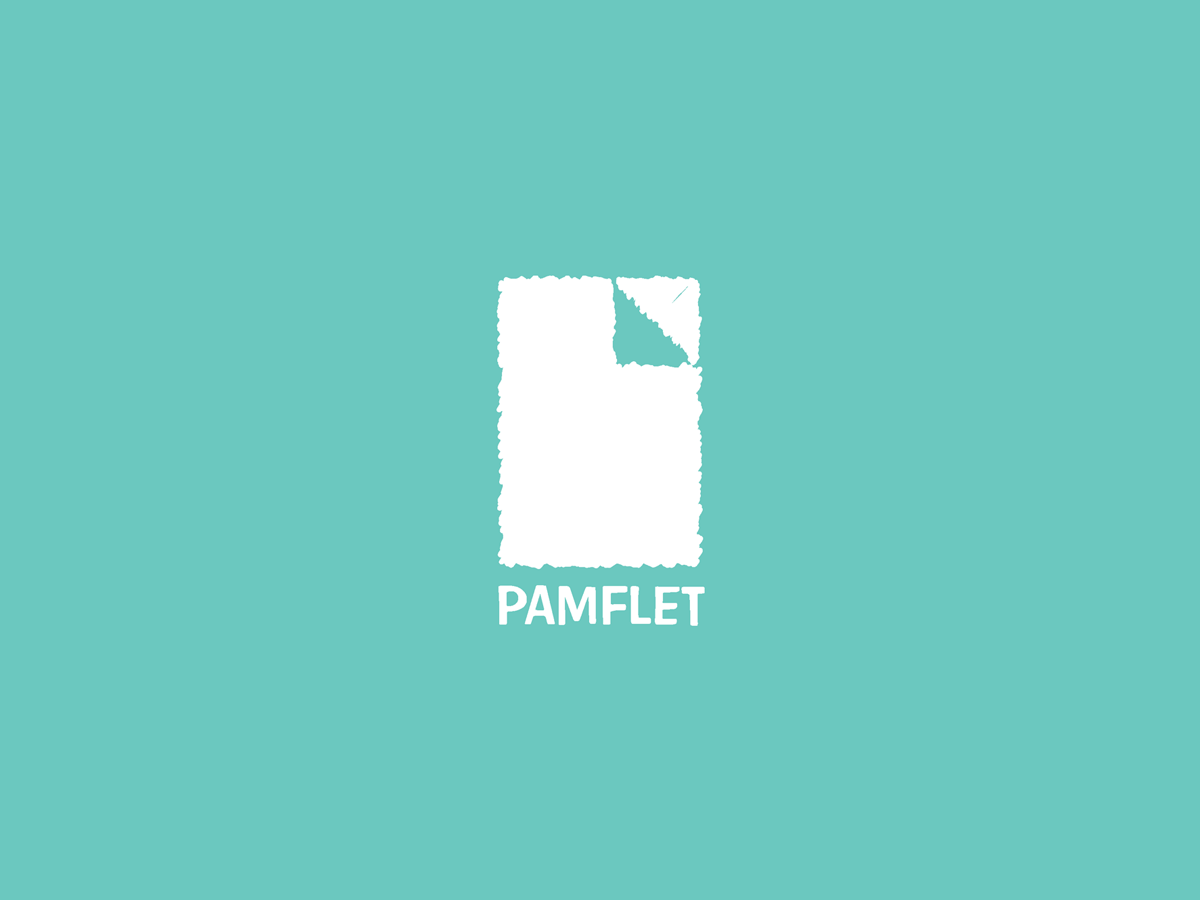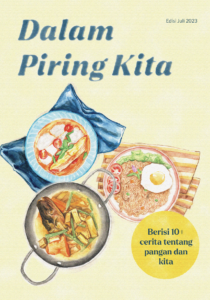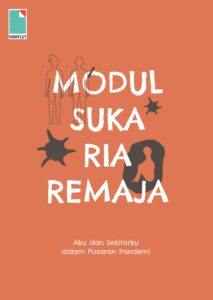Rumah saya dulu selemparan batu dari Lubang Buaya. Bahkan sejak kecil, saya selalu terpana melihat gerbang megah Monumen Pancasila Sakti dan penasaran apa yang ada di ujung jalan masuk yang panjang itu. Suatu ketika, orang tua saya memenuhi rasa ingin tahu saya dan membawa saya masuk Monumen tersebut. Saya menatap heran pada diorama-diorama kaku, buku panduan pengunjung yang berwarna merah darah, dan pameran baju korban yang masih menyisakan bekas darah. Jujur, saya merasa tidak nyaman. Museum itu bau anyir. Ruangannya gelap dan sunyi. Lubang yang terkenal itu disinari lampu neon murahan dan penuh slogan dramatis serta foto-foto sadis.
Saya tidak pernah kembali ke Lubang Buaya sejak saat itu. Ada perasaan kosong di sana yang masih membekas dalam diri saya sampai sekarang. Konon katanya, lima puluh tahun yang lalu, sebuah kekuatan politik yang kurang ajar membelot dan membunuh tujuh pahlawan bangsa: enam orang Jenderal kenamaan, dan satu orang tentara yang tidak karuan sialnya. Tetapi Indonesia tak mau digoncang. Kita menumpas pemberontakan itu dengan heroik, dan keteguhan Pancasila bertahan dari rongrongan setan Komunis yang makar. Sisanya, kita anggap, adalah sejarah.
Perlu waktu yang sangat lama bagi saya pribadi untuk menyadari betapa sempit dan dangkalnya pengertian sejarah yang satu ini. Sekarang kesempatan kita untuk belajar bahwa kisah G-30S tidak berhenti pada tanggal 30 September 1965. Bahwa “setan yang berdiri mengangkang” itu agaknya belum berhasil dibongkar pada 21 Mei 1998. Yang terjadi sebelum, ketika, dan setelah 30 September 1965 adalah sejarah yang jauh lebih rumit ketimbang sekedar kisah penumpasan pemberontakan. Jangan sampai kita – meminjam istilah Koil – terus “merasa benar-benar pintar memasyarakatkan kebodohan” ini.
Jangan berhenti membaca